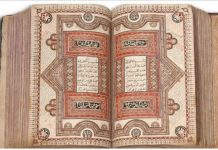Kepentingan pemerintah atas pengeluaran kebijakan sastra sebagai bagian dari kurikulum pendidikan meninggalkan polemik. Perdebatan bertumpah ruah dalam ruang nyata maupun maya.
Betapapun, terlepas dari itu semua, kiranya kita semua sepakat bahwa keberadaan sastra sangatlah penting bagi tumbuh kembang hidup seorang manusia. Dalam makna sederhana, sastra adalah tempat pencarian identitas, mengasah imajinasi, mengolah batin, dan melatih kemampuan berpikir kritis.
Dengan melakukan kontekstualisasi, maka keberadaan sastra sah dikenalkan sejak dini bagi kalangan anak. Sebab, proses mereka panjang, sehingga kehadiran sastra menjadi stimulus pertumbuhan fisik dan mentalnya dan kemudian menjadi bagian integrasi terhadap perubahan zaman yang dihadapi.
Perubahan zaman dalam konteks sains dan teknologi, membuat kesastraan disajikan dalam produk bacaan menuntut perubahan imajinasi atas kompleksitas yang terjadi
Berhubungan dengan sastra anak, terdapat buku penting garapan dari Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak (2005). Salah satu yang ditekankan oleh Burhan adalah keberadaan fiksi sains.
Jelasnya, “Cerita fiksi tentulah dikembangkan di sekitar kehidupan manusia, permasalahan manusia, dan dengan penyelesaian manusia, tetapi semuanya berlangsung dalam lingkup ilmiah.” Dalam babak perkembangan sastra anak, di Majalah Tempo edisi 25 Juli 1999 pernah menurunkan sebuah liputan berjudul “Menyusuri Buku Sastra Anak”.
Uang Panai’ dan Gengsi Sosial
Kenyataan yang tak bisa ditampik, fiksi sains di Indonesia sulit bertumbuh. Arkian, kelegaan orang tua dan anak-anak untuk mengikuti perkembangan sains dan teknologi dalam bentuk sastra sangat terbantu dengan karya sastra terjemahan. Penulis yang justru membentuk anak-anak di antaranya adalah Lewis Carrol, H. C. Andersen, hingga J. K. Rowling. Di manakah fiksi ilmiah di Indonesia? Di liputan justru terdapat kritik yang disampaikan: “Penulis cerita anak Indonesia kurang riset”.
Membaca Sastra
Hal yang sama pernah diungkap oleh ahli sastra anak Murti Bunanta. Melalui esai “Perjuangan untuk Bacaan Anak yang Layak” dalam bunga rampai Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita (2000), ia meresahkan akan bagaimana buku berjenis fantasi dan fiksi ilmiah masih sangat minim.
Memang, keberadaan pengarang Indonesia di kancah fiksi sains masih terbilang sedikit. Ada beberapa nama yang bisa disebut, di antaranya Djokolelono, Lia Cyntia, Eliza V. Handayani, hingga H. Zubir Mukti.
Namun, nama-nama itu tercatat aktif di antara era 1970-an hingga awal 2000-an. Hal yang kemudian perlu direfleksikan adalah terhadap situasi mutakhir. Persoalan fiksi sains jarang menjadi bahasan dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Bukankah itu sejatinya makin penting, terlebih dalam situasi zaman yang diwarnai perubahan ilmu yang cepat dan ditandai dengan kemunculan teknologi yang makin kompleks?
Kenyataan itu sungguhlah mengkhawatirkan. Pergulatan dalam tautan teks di kalangan anak di era mutakhir sangatlah mengalami perubahan berarti, katakanlah ketimbang mereka yang secara kebiasaan lebih mudah mengoperasikan produk teknologi.
Apa yang perlu direlevansikan akan perkembanganan sastra? Jikalau sastra sebagai produk hanya berpangkal pada paradigma umum yang menyiratkan pelanggengan sastra sebagai barang “adiluhung” yang seakan stagnan maupun tidak bisa dikembangkan lagi.
Hal tersebut menegaskan apa yang ditulis Ignas Kleden (1988). Kebutuhan fiksi sains di telinga anak-anak justru hanya terpenuhi dari penulis luar. Minimnya penulis Indonesia menjadi keresahan Ignas berupa pembacaan jangka panjang akan situasi yang terjadi pada proses tumbuh dan kembang anak.
Bahwa, memang kebutuhan berimajinasi terpenuhi, namun anak-anak bisa jadi mengalami kehilangan akan identitas dalam konteks kebudayaan Indonesia.
Perubahan Imajinasi
Setakat dengan hal itu, kecerdasan dalam transformasi zaman senantiasa mengalami evolusi. Pada perkembangan kecerdasan buatan, matematikawan Iwan Pranoto (2023) pernah menjelaskan, dengan perkembangan teknologi, manusia harus siap berdampingan dengan mesin cerdas serta mungkin berperasaan di masa depan. Bagi Iwan, ragam kolaborasi manusia-mesin seperti itu dapat diperkirakan akan paling banyak bermunculan di masa depan.
Jika keberadaan sastra masih diharapkan menjadi galah, tentu ada hal yang patut direnungkan. Perubahan zaman dalam konteks sains dan teknologi, membuat kesastraan disajikan dalam produk bacaan menuntut perubahan imajinasi atas kompleksitas yang terjadi.
Kemungkinan demi kemungkinan yang terkadang mengkhawatirkan kemanusiaan dapat dijembatani dengan sastra yang menghaluskan rasa. Dengan begitu, perkembangan sains dan teknologi tidak radikal menjadikan generasi hanya berpikir linier tanpa merenungkan kehidupan komunal, lingkungan, etika, hinga kemanusiaan.
Suara Satu Aksi, Bersatu untuk Bumi
Arkian, kita tidak boleh sebatas mengatakan sastra penting dalam pendidikan, namun juga membaca secara gradual. Logika ini bisa diambil dalam beberapa contoh.
Jika fiksi sains hanya mengenalkan nama teknologi, apa bedanya dengan narasi bacaan di beberapa tahun lalu? Jika produk sastra membicarakan krisis iklim hanya sebatas menganjurkan membuang sampah tidak sembarangan, apa bedanya dengan bacaan di zaman Orde Baru?
Pelajaran Sastra
Jika sastra membawa misi hanya menyampaikan ajakan menanam pohon, apa bedanya dengan sastra di halaman majalah era 1980-an? Sastra dalam abad XXI agaknya membutuhkan korelasi terhadap tinjauan perkembangan ilmu. Agar hadirnya terus relevan dan menjadi jembatan mendasar berupa penyuguhkan nilai, prinsip, dan makna untuk perenungan zaman.
Di sisi lain, anak-anak terbiasa mudah dalam menggunakan maupun mengoperasikan ragam teknologi dengan ditopang tayangan video di media sosial, film, hingga gim. Tanpa kemauan untuk menelaah jauh, bisa jadi keberadaan sastra, alih-alih memikul kepentingan penyadaran, justru terkesan tidak dibutuhkan generasi zaman ini.[]