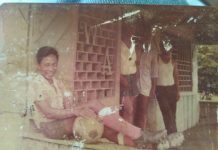Sejak kecil kita diajarkan untuk menabung. Buku tabungan pelajar dibagikan di sekolah dasar, dengan harapan menanamkan kebiasaan baik sejak dini. Namun seiring bertambah usia, kita mulai sadar, bahwasannya untuk bisa menabung, kita harus terlebih dahulu memiliki sisa dari pengeluaran. Dan pada titik ini, kenyataan tak semanis nasihat buku pelajaran.
Kapan hari, salah seorang teman karib saya bercerita keluh tentang dampak pemangkasan anggaran rezim Prabowo. “Efisiensi dampaknya luar biasa, Mas”, ujarnya. Pemangkasan itu berdampak pada aktivitas sekaligus ritme kerjanya.
Teman saya ini, sehari-hari bekerja di salah satu lembaga bantuan hukum non-profit yang berkantor di Surakarta. Ia sering bercerita, sebelumnya rutin memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang butuh, terutama mereka yang kurang mampu dan tidak memiliki akses ke sistem peradilan.
Akibatnya, teman saya kalang kabut merespons kebijakan serampangan ini. “Anggaran tahun sebelumnya itu bisa mencapai 100 juta per tahun. Kali ini tinggal kurang dari 20 juta”. Uang 20 Juta, menurutnya hanya mampu mendampingi sekitar 2-3 kasus saja. Padahal, setiap tahunnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bisa menangani puluhan sampai ratusan kasus yang sifatnya pro bono.
“Kasihan masyarakat kecil jadinya, Mas”, ungkapnya prihatin.
Saya pribadi memandang dampak ini tidak hanya menyusahkan mereka yang butuh bantuan hukum. Teman saya juga terimbas langsung. Uang pribadi pasti ikut kalap dalam rantaian anggaran itu. Padahal di rumah, Ia mesti hidup-menghidupi keluarga kecilnya.
Dengan nada gurauan, saya tanya, “sering tombok jadinya, Pak?”
“Ya bagaimana lagi, Mas” jawabnya pasrah.
Di tempat yang lain, di sebuah sudut kota yang memiliki slogan The Spirit of Java, salah seorang perempuan muda berdiri di depan warung kecilnya. Ia berusia 29 tahun, seorang ibu dari dua anak yang setiap harinya bekerja sebagai buruh cuci sekaligus penjaga warung milik saudaranya. Setiap bulan, ia meraup pendapatan hanya berkisar Rp1.500.000 hingga Rp.2.000.000. Ketika ditanya apakah bisa menabung, ia tersenyum miris, “bukan saya tidak ingin, tapi cukup untuk makan saja sudah bersyukur.”
Baca juga: Menjadi Penulis
Kisah ini sering saya renungkan sendiri, dan mungkin kisah Ibu tadi bukan satu-satunya. Jutaan masyarakat Indonesia hidup dalam kungkungan realitas serupa. Mereka bukan tidak tahu pentingnya menabung. Bahkan banyak yang sudah sejak kecil dididik dengan pesan nan bijak, “hemat pangkal kaya.” Namun, ketika penghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup harian, menabung menjadi kemewahan yang hanya bisa diimpikan.
Dalam konteks inilah, saya sering mempertanyakan “Bukan Kita Tak Mampu Menabung” menjadi refleksi sosial yang dalam: ini bukan soal kemalasan atau boros, tapi tentang ketimpangan struktural dan realitas ekonomi yang mencekik rakyat kecil.
“Kemiskinan bukanlah akibat dari pilihan buruk individu semata, melainkan hasil dari sistem yang belum mampu menjamin pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Banyak orang membanting tulang dari pagi hingga malam, tetapi seumur-umur tetap pas-pasan, karena struktur ekonomi yang timpang”
Di tengah himpitan ekonomi yang semakin membenam-memberat, banyak pekerja di Indonesia mengeluh tentang sulitnya menabung. Upah yang diterima sering tak sebanding dengan biaya hidup yang terus melambung. Setiap bulan, gaji habis untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, listrik, air, dan biaya pendidikan anak. Tepat ketika semua kebutuhan dasar terpenuhi, nyaris tak ada sisa pundi-pundi rupiah untuk disimpan, dijadikan tabungan.
Persoalan ini sering disalah-artikan sebagai ketidakmampuan individu dalam mengelola keuangan, atau kerap disebut sebagai kurang melek literasi finansial. Padahal, akar masalahnya lebih dalam lagi: upah yang rendah dan ketimpangan ekonomi. Bukan berarti masyarakat tak ingin menabung. Bukan. Tetapi kondisi ekonomi membuat mereka terjebak dalam lingkaran hidup dari gaji ke gaji.
Kemiskinan Bias Akibat Gaya Hidup
Ada kecenderungan dalam masyarakat dan media untuk menyederhanakan masalah ekonomi individu dengan menyalahkan gaya hidup. Misalnya, kampanye-kampanye keuangan yang menyarankan untuk mengurangi minum kopi kekinian atau berhenti langganan streaming supaya bisa menabung. Meski niatnya edukatif, pendekatan ini cenderung mengabaikan akar persoalan yang ada, yakni rendahnya pendapatan dan tingginya biaya hidup.
Maraknya konten literasi keuangan personal di media sosial kadang mencipta narasi semu, bahwa siapapun bisa kaya jika disiplin. Padahal, tanpa menafikan pentingnya literasi keuangan, ada fakta ekonomi yang tak bisa diselesaikan hanya dengan mengatur uang jajan atau menahan pengeluaran. Seorang pekerja harian dengan penghasilan Rp.2.000.000 per bulan, setelah dipotong biaya sewa, makan, dan transportasi, nyaris tak memiliki sisa. Dalam situasi ini, bukan disiplin yang kurang, sebenarnya, melainkan keadilan ekonomi yang absen.
Kemiskinan bukanlah akibat dari pilihan buruk individu semata, melainkan hasil dari sistem yang belum mampu menjamin pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Banyak orang membanting tulang dari pagi hingga malam, tetapi seumur-umur tetap pas-pasan, karena struktur ekonomi yang timpang.
Baca juga: Jejak Budaya dan Nurani Manusia
Jika melampau ke masa lalu, sejak kecil kita sesungguhnya sudah diajarkan untuk menabung. Buku tabungan dengan tone satu warna dengan logo tut wuri handayani dibagikan ke pelajar di sekolah dasar, dengan harapan menanam kebiasaan baik menabung sejak dini. Namun, seiring bertambah usia, kita mulai sadar, bahwa untuk bisa menabung, kita harus terlebih dahulu memiliki sisa pengeluaran. Dan pada titik ini, kenyataan tak pernah semanis nasihat buku pelajaran.
Banyak dari kita hidup di antara dua titik genting, yaitu “cukup” dan “tidak cukup”. Ketika penghasilan minimum hanya sebatas upah minimum provinsi (UMP) yang tak sebanding dengan kebutuhan hidup layak, maka menabung bukan lagi prioritas. Bahkan, meminjam uang sering jadi satu-satunya jalan agar dapur tetap mengepul.
Upah dan Kebutuhan
Di Indonesia, UMP sering kali tak cukup memenuhi kebutuhan hidup layak. Bagi seorang pekerja yang harus menyewa rumah, membayar ongkos mobilitas, makan, dan biaya sekolah anak, jumlah gaji yang diterima bisa habis dalam sebulan tanpa barang sepeser.
Bagi buruh pabrik atau pekerja sektor informal seperti ojek online, pedagang kecil, atau tenaga harian, upah mereka bahkan (jauh) lebih rendah dari UMP. Mereka harus bekerja ekstra—kadang lebih dari 12 jam sehari—hanya untuk bertahan. Ya, bertahan hidup. Dalam situasi seperti ini, menabung menjadi kemewahan yang sulit dijangkau.
Pemikiran Karl Marx masih sangat relevan dalam menjelaskan kondisi tindas-menindas ini. Di mana sistem kapitalis, buruh sering dieksploitasi dengan upah rendah sementara nilai lebih (surplus value) hasil kerja mereka dinikmati oleh pemilik modal. Fenomena ini terlihat jelas di sekitar kita hari ini, di mana banyak pekerja menerima upah minimum sementara perusahaan meraup keuntungan besar.
Lebih dalam, Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, dalam bukunya The Price of Inequality (2012) membeberkan bahwa ketimpangan ekonomi terjadi ketika sistem politik dan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang. Di Indonesia, hal ini terlihat dari kesenjangan antara upah buruh dan gaji eksekutif perusahaan yang bisa mencapai ratusan kali lipat.
Masalah Struktural
Masalah ketidakmampuan menabung bukan semata-mata kesalahan individu, sungguh, melainkan akibat sistemik upah rendah dan ketimpangan ekonomi. Selama kebijakan upah tidak berpihak pada kaum pekerja, selama itu pula masyarakat niscaya sulit menyisihkan uang demi tabungan.
Perlu perubahan struktural—dari kenaikan upah yang manusiawi, perlindungan sosial yang kuat, hingga sistem ekonomi yang lebih adil. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi juga memiliki kesempatan menabung dan merencanakan masa depan yang lebih baik.
Bukan kita tak mampu menabung, justru sistem yang akut sering tidak memberi kita kesempatan melakukannya. Bukan kita tak mampu menabung, tetapi sistem ini membuat kita terus berada dalam situasi bertahan hidup.
Bahwa di balik setiap dompet kosong, ada kisah panjang perjuangan, ada struktur ekonomi yang timpang, dan ada harapan agar suatu hari kelak, menabung bukan lagi menjadi previlese, tapi bagian dari kehidupan yang “menyehari” bagi semua lapisan sosial.