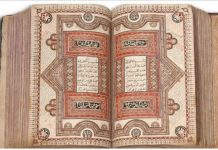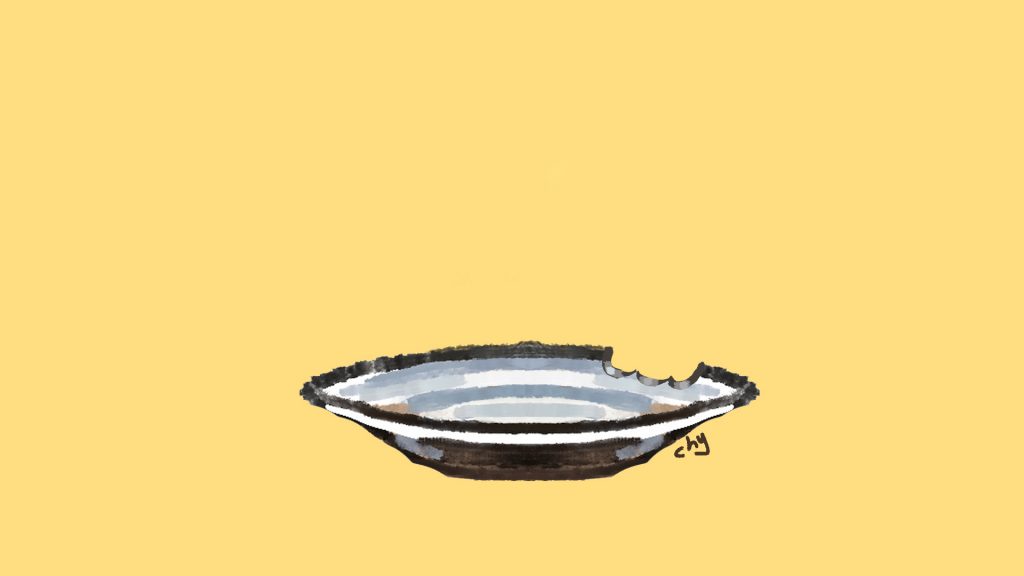
Bermula dari obrolan kusir tentang etika dan estetika, saya tergerak untuk menulis tentang keduanya. Etika berkaitan erat dengan baik-buruknya tingkah laku.
Predikat susila dan asusila melekat secara sah di dalamnya, sehingga etika termasuk dalam kawasan nilai. Sementara itu, estetika menyangkut kadar indah-jelek yang dapat dimaknai secara luas, sempit, maupun murni.
Namun, bahasan etika dan estetika ini bukan menyoal dalam pergaulan, melainkan pemaknaannya dalam budaya. Tidak dapat dihindari, pusparagam budaya di Indonesia menjadi begitu magnetis di kalangan orang asing, memantik banyak aspek semacam telaah, penelitian, bahkan penilaian dari ekspresi budaya itu sendiri.
Termasuk segala ide dan aktivitas sosial-budaya di dalamnya yang kerap tersorot-kagumi oleh Masyarakat asing. Ironinya, keragaman budaya dan tradisi lokal justru menuai kritik dan cemooh dari Masyarakat domestik itu sendiri.
Tardisi Tawur Nasi
Di daerah Demak misalnya, tepatnya di Desa Jleper Kecamatan Mijen terdapat satu tradisi yang masuk dalam rangakaian kegiatan sedekah bumi, berupa tawur nasi yang dilakukan pasca pembacaan tahlil dan doa. Tawur nasi dilakukan oleh masyarakat dan para pemuda dari dusun lor dan kidul.
Perang nasi dilakukan bukan sebab saling dendam, melainkan semacam selebrasi sebagai wujud rasa syukur dan kegembiraan atas limpahan rezeki yang diberikan Tuhan. Setelahnya, nasi-nasi yang beserakan akan dikumpulkan sebagai pakan ternak, sehingga dalam tradisi tersebut tidak terjadi mubadzir terhadap makanan.
Tradisi semacam ini memantik kontra dari warga lain yang tidak tergabung di dalamnya. Mereka menyampaikan sentimentil, mengkritik, bahkan mencemooh dengan berbagai ungkapan negatif. Padahal, jika kita menengok kembali substansi budaya, tradisi tersebut sah-sah saja.
Baca juga: Seikat Risalah dari Ceramah
Menilik pemikiran Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mereka merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Konsep cipta, rasa, dan karsa menjadi aspek fundamental yang membentuk dan mewarnai seluruh ekspresi kebudayaan.
Konsep ini menggambarkan bagaimana manusia menciptakan, merasakan, dan menggerakkan kebudayaan melalui paduan pemikiran, perasaan, serta tekad untuk menjaganya. Dengan demikian, manusialah yang membentuk dan mengembangkan budaya.
Budaya sebagai hasil karya manusia sesungguhnya diupayakan untuk memenuhi unsur keindahan. Sebab, sejatinya manusia menyukai keindahan, sehingga berusaha untuk berestetika dalam budaya yang diciptakannya
Selain itu, The World of Man oleh J.J. Hoenigmann yang juga diadopsi oleh Koentjaraningrat secara sederhana menerangkan tiga wujud budaya sebagai aspek terbentuknya sebuah budaya berupa mentifak (ide), sosiofak (aktivitas sosial), dan artefak (benda). Sebuah budaya yang lahir tentu atas hasil dari gagasan, ide, pemikiran serta kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Sehingga memunculkan aktivitas sosial-budaya yang dapat diamati, dilihat, dan dilaksanakan.
Kerap kali sebagian orang hanya memaknai budaya sebagai wujud material semata. Padahal, lebih dari itu, Soerjono Seokamto dalam bukunya yang bertajuk Sosiologi sebagai pengantar tidak melulu menyoal material, tetapi juga immaterial atau istilah yang akrab digaungkan adalah (meterial culture dan spiritual atau immaterial culture). Secara falsafah dan historis budaya atau tradisi yang berjalan di masyarakat menjadi identitas, keunikan, dan kekayaan daerah tersebut.
Artinya, secara fisik dan batin kebudayaan memiliki unsur yang dapat diraba dan dirasakan. Tugas manusia adalah berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyerasikan perilaku terhadap kaidah-kaidah melalui etika, dan mendapatkan keindahan melalui estetika.
Etika Manusia
Manusia yang beretika akan menciptakan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Etika budaya mengandung tuntutan atau keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung nilai-nilai etik yang dapat diterima sebagian besar orang. Khususnya dalam Masyarakat itu sendiri, saya tuliskan “sebagian” sebab bisa jadi di luar daerah tersebut tidak menyetujui budaya yang ada.
Budaya yang memiliki nilai etika adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pun dengan estetika budaya, sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur keindahan. Budaya yang estetik adalah budaya yang memiliki unsur keindahan.
Baca juga: Angleluri Kabudayan Jawi
Budaya sebagai hasil karya manusia sesungguhnya diupayakan untuk memenuhi unsur keindahan. Sebab, sejatinya manusia menyukai keindahan, sehingga berusaha untuk berestetika dalam budaya yang diciptakannya. Saya percaya, semua budaya pasti dipandang memiliki nilai-nilai etika dan estetika bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Mirisnya, Sebagian orang justru sentimentil dan memandang rendah budaya orang lain tanpa lebih dulu mencari tahu falsafah dan historisnya.
Meski etika dan estetik bersifat subjektif, tetapi kita dapat melepaskan subjektivitas tersebut untuk melihat etika dan estetika dari budaya lain. Estetika budaya tidak semata-mata keindahan dalam budaya.
Namun lebih dari itu, estetika budaya menyiratkan perlunya manusia (individu atau masyarakat) untuk menghargai keindahan yang dibuat oleh manusia. Maka dengan demikian, estetika berbudaya yang demikian akan mampu memecah sekat-sekat kebekuan, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan inferioritas antarbudaya.
Masyarakat harus paham, peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bahwa konteks budaya dalam adat istiadat dan norma sosial mengajak seseorang harus menghormati dan mengikuti adat istiadat serta norma-norma yang berlaku di tempat di mana ia berada atau tinggal.
Selama seseorang tidak menghormati budaya di sekitarnya, di luar daerahnya, maka selama itu pula narasi kritik, intoleran, dan sentimentil terhadap budaya lain akan selalu lahir.