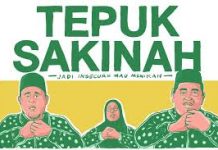Malam itu, Kamis Wage pasaran pertama bulan Oktober, saya memberanikan diri untuk silaturahmi, tabarukan, ber-tabayyun serta melantunkan doa kepada leluhur trah Pengging. Waktu itu, baik di pasarean Ki Ageng Pengging Sepuh (Andayaningrat)—putra Ki Ageng Kebo Kenongo sampai pasarean Pujangga Kasunanan Surakarta Tus Pajang R. Ng. Yasadipura I dan II ramai dikunjungi peziarah.
Sepenuturan teman saya yang sering nyarkub (sarjana kuburan, sebutan bagi orang yang sering ziarah), kawasan Pengging memang ramai dikunjungi khalayak.
Motif orang-orang yang datang kesini memang beragam, ada yang murni berziarah-tabarukan dengan sesepuh Pengging, hendak mujahadah atau melangitkan doa-doa, pun ada yang berniat kungkum (berendam) di umbul sebagai laku tirakat—bahkan sampai tindakan yang berkonotasi negatif seperti mencari pesugihan atau mencari nomor togel.
Mafhum, kiranya kejadian tersebut terjadi sebab keislaman orang Jawa dikenal berkelindan dengan hal-hal mistis. Namun, hal yang acap keliru bahkan diamini banyak orang yakni mistis dianggap sebagai ajaran tentang kekuatan supranatural yang datang dari benda. Suatu barang yang diyakini mempunyai daya magis dan mampu memberi kekuatan tertentu.
Hal ini tentu berseberangan dengan Islam dan menyekutukan Allah Swt. Padahal ajaran mistisisme Islam-Jawa berakar dari ajaran sufisme para Pujangga Keraton dan Waliyullah (Walisongo) penyebar Islam di tanah Jawa. Dalam mana merupakan ajaran tasawuf untuk mencapai makrifat kepada Tuhan lewat laku (suluk) tirakat, zuhud, menyucikan hati, serta berserah diri kepada Allah Ta’ala.
Keberislaman orang Jawa juga turut memancing banyak kalangan untuk mengkajinya lebih jauh, tak terkecuali para orientalis—sebutan untuk peneliti Barat yang mengkaji Timur (dalam konteks ini Jawa).
Sebermula masa Kolonialisme Hindia-Belanda, pascakekalahan Perang Jawa (perang sabil) pribumi Islam yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan jaringan ulama serta pengikut tarekat syattariyah melawan penjajah (landha kapir).
Baca juga: Ritual Mahesa Lawung di Alas Krendowahono
Irfan Afifi dalam Saya, Jawa dan Islam (2019) menuturkan perihal usaha sistematis Kolonial dalam mendegradasi Islam sebagai identitas penyatu dan penyangga pondasi keberislaman masyarakat Jawa.
Tindakan ini dimulai dengan diberlakukannya sistem tanam paksa atau cultur stelsel (1830). Selang 2 tahun, kemudian didirikan lembaga khusus kajian Jawa dan Sastra Jawa yang bernama Het Instituut voor de javanesche Taal 1832 (baca: Institut Javanologi).
Dengan produk kajian Javanici ini, pihak Kolonial berupaya menciptakan imaji bahwa Islam merupakan agama yang kasar, revolusioner, sinkretik dan jauh dari nilai Jawa nan esensial.
Begitu besar rasa traumatik dan kerugian material yang diderita Pemerintah Kolonial sehingga berbagai jalan pun ditempuh guna memisahkan Islam dalam kultur masyarakat Jawa.
Kali ini, kita akan membahas tentang Pengging atau dalam historiografi Jawa dikenal dengan Kadipaten Pengging. Sebuah tlatah perdikan hadiah dari Brawijawa V berkat kesetiaan penguasanya, yakni Sri Mangkurung Andayaningrat atau yang kawentar dengan sebutan Ki Ageng Pengging Sepuh.
Kesetiaan Ki Ageng Pengging Sepuh hadir terbukti berkat jasanya menaklukan Jawa ujung timur, yakni Blambangan dan Bali. Upaya penaklukan tersebut juga dibantu oleh Sapu Laga dari Probolinggo. Ki Ageng Pengging Sepuh akhirnya berhasil mengalahkan Raja Menak Bandong dari Denpasar (Purwadi, 2012: 257).
Atas balas budi jasa tersebut, walhasil diberilah tanah perdikan Pengging beserta kesempatan istimewa untuk mempersunting salah satu putrinya, Ratna Pembayun. Hasil dari pernikahan tersebut lahirlah tiga orang putra yakni Ki Ageng Kebo Kanigara, Ki Ageng Kebo Kenongo, dan yang terakhir adalah Raden Kebo Amiluhur.
Dari ketiga putra tersebut, hanya Ki Ageng Kebo Kenongo (Ki Ageng Pengging II) yang berhasil melahirkan keturunan yang kelak menjadi penguasa Jawa usai Kasultanan Demak Bintoro surut.
Raden Mas karebet—atau yang kelak bergelar Sultan Hadiwijaya, penguasa Kerajaan Pajang Hadiningrat—merupakan keturunan Ki Ageng Kebo Kenongo.
Pengging, Identitas Islam dan Simbol Budaya
Sri Mangkurung Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh merupakan penguasa tlatah perdikan Pengging. Purwadi dalam Babad Demak: Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa (2012) menjelaskan asal usul menantu Brawijaya V itu.
Purwadi menuturkan bahwa Andayaningrat juga dikenal dengan nama Jaka Bodo dan Jaka Sangara. Nama Sangara sendiri disinyalir merupakan marga dari ayahnya yang bernama Bajul Sangara dari Semanggi. Ia dijelaskan merupakan penguasa masyarakat Bajul (buaya).
Sumber lain justru mengatakan hal yang berbeda. Menurut Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali dalam papan informasi yang terpancang di depan gerbang Pasarean Ki Ageng Pengging Sepuh, seperti yang saya lihat dan baca, menyebut nama asli Ki Ageng Pengging Sepuh ialah Syarif Kabungsuwan/Sayyid Muhammad Kebungsuan, putra bungsu dari Sayyid Husein Jumadil Kubro hasil dari perkawinan dengan Putri Jauhar asal Kerajaan Muar Lama, Malaysia.
Menarik rupanya menelisik asal muasal Raja pertama tlatah Pengging ini. Muncul dua argumentasi. Pertama jika memang Ki Ageng Pengging Sepuh putra dari Bajul Sangara berarti ia belum memeluk agama Islam dengan kata lain ia masih menjadi pemeluk agama Hindhu-Siwa.
Kedua, bila benar Ki Ageng Pengging Sepuh merupakan keturunan Sayyid Jumadil Kubro, sudah dapat dipastikan bahwa ia merupakan pemeluk Islam yang taat, mengingat Sayyid Jumadil Kubro merupakan ulama senior di tanah Jawa.
Berbagai argumentasi muncul seiring maraknya penelitian tentang sosok kharismatik yang hidup sekitar abad ke-15 ini. Wajar kiranya hal demikian terjadi.
Baca juga: Citra Diri Perempuan Jawa dan Gerak Transendental
Saya lebih tertarik untuk membaca simbol-simbol budaya yang ada di pasarean Ki Ageng Pengging Sepuh. Belakangan, semakin jarang seseorang yang dapat memahami simbol budayanya sendiri. Jangankan untuk memahami, rasa ingin tahu dan ketertarikan itu pun tampaknya pudar.
Sistem pendidikan-pengajaran dengan perangkat kurikulumnya juga tidak mengajarkan hal ini. Kecurigaan saya berawal dari ditetapkannya kebijakan Politik Etis (1901) perihal pendidikan.
Pengaruh pendidikan gaya Barat tampaknya mempengaruhi sistem sosial-kultural di Indonesia. Walakin, dewasa ini minat pada bahasa lokal yang menjadi identitas diri terkikis. Ini tidak bisa tidak berimplikasi pada pemahaman pembacaan simbol budaya.
Sekitar Pesarean Ki Ageng Pengging Sepuh
Pasarean inilah yang mengantarkan saya untuk membaca simbol budaya kita. Frasa pasarean sendiri berasal dari kata “sare” tidur, jadi pasarean mengandung makna sebagai ‘tempat berbaring’, ‘tempat peristirahatan bagi orang yang sudah meninggal’.
Frasa pasarean sendiri berasal dari kata “sare” tidur, jadi pasarean mengandung makna sebagai ‘tempat berbaring’, ‘tempat peristirahatan bagi orang yang sudah meninggal’.
M Yaser Arefat dalam buku Nisan Hanyakrakusuman: Batu Keramat dari Pasarean Sultanagungan di Yogyakarta (2021), menguraikan sederet istilah makam atau kuburan di Indonesia. Sebut saja astana, setana, asta, astano, ustano, njratan, jirat, pasarean, sasanalaya, dsb.
Dalam kasus Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Timur, istilah pasarean-lah yang umum kita jumpai.
Selain itu, M. Yaser Arefat juga mendedahkan anatomi pasarean mulai dari nisan, kijing atau jirat, cungkup, bahkan pepohonan. Saya pun terpancing dan mulai melakukan riset kecil-kecilan, menelusuri aneka simbol budaya yang ada di pasarean Ki Ageng Pengging Sepuh.
Anatomi-anatomi di area makam tersebut tak hanya dibuat tanpa dasar filosofis yang jelas, justru sebaliknya. Struktur dibangun sebagai manifestasi material atas sistem kebudayaan yang berlaku di suatu masa.

Sekilas, bagi orang awam pasti akan merasa bingung tatkala kali pertama datang ke pasarean ini. Peziarah tentu akan disuguhi pemandangan pasarean dengan nuansa warna kuning kunyit (mustard).
Sebuah pohon raksasa nan besar bernama pohon kepoh (sterculia feotida) juga turut mengundang perhatian bersama. Kini, raksasa itu sudah tumbang dan sisa batang yang masing menjulang dibalut kain berwarna kuning. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan pada pohon tersebut.
Pohon unik nan langka memang sering dijumpai di makam. Gunung, air dan pohon merupakan titik sentral kepercayaan masyarakat Jawa, bahkan sebelum ajaran Hindhu-Buddha datang. Hal ini merupakan kelanjutan dari sistem spiritual masyarakat Jawa.
Jangan heran apabila banyak makam-makam leluhur yang terdapat pohon besar yang menjulang tinggi, seperti menusuk angkasa. Pohon merupakan simbol tempat pensucian dalam nalar spiritual masyarakat Jawa.
Selain pohon, anatomi pasarean ini juga terdapat nisan dan kijing berlanggam Demak-Tralaya. Sebagaimana penuturan M. Yaser Arafat, nisan-nisan semacam ini masuk dalam tipologi nisan Demak-Tralaya. Yang mana mempunyai ukuran relatif besar dengan tinggi 50-55 cm tanpa ragi hias kembang awan di badan nisan.
Sebagaimana penuturan M. Yaser Arafat, nisan-nisan semacam ini masuk dalam tipologi nisan Demak-Tralaya. Yang mana mempunyai ukuran relatif besar dengan tinggi 50-55 cm tanpa ragi hias kembang awan di badan nisan.
Hal yang menarik perhatian lainnya datang dari payung bersusun tiga tingkat dengan warna kuning kunyitnya. Payung sendiri merupakan interpretasi dari simbol kekuasaan sesosok tokoh yang harus dihormati, mempunyai karamah dan jiwa karismatik tinggi.
Payung sendiri merupakan interpretasi dari simbol kekuasaan sesosok tokoh yang harus dihormati, mempunyai karamah dan jiwa karismatik tinggi.
Sedang makna dari tiga susun merupakan pengejawantahan dari sifat Iman-Islam-Ihsan. Warna kuning sendiri merupakan perlambang dari senye, tanda kekuatan dari sinar atau cahaya. Sejak era Mataram Islam, warna kuning memang selalu menjadi penghias anatomi tubuh pasarean di Jawa. Mulai dari hiasan di kuncup, payung, dan untaian kain yang serba kuning. Lihat saja.
Dengan kata lain, lewat pembacaan simbol-simbol budaya di pasarean ini, dapat ditarik simpulan bahwa ganda (aroma) Islam sudah lekat pada tokoh yang disemayamkan di sini. Mulai dari arah nisan yang membujur dari utara ke selatan, kemudian simbol payung bertingkat tiga yang kental dengan nuansa Islam.
Pasarean memberi kawruh (ilmu) tentang bagaimana suatu tradisi menjadi tonggak kebudayaan. Pasarean merupakan sarana sumber pengetahuan tentang suatu kebudayaan.
Pasarean pun termasuk dari “Sapta Mandala Srawung”, yaitu sebagai tujuh tempat pergumulan aktivitas sosial-budaya masyarakat Jawa yang terdiri dari omah, lurung (jalan), langgar, pasar, donya jembar (sekarang bisa kita maknai sebagai ruang interaksi virtual: media sosial), tuk (mata air) dan pasarean (pemakaman).
Konon, gagasan ini dicetuskan oleh Ki Ageng Juru Mertani, salah seorang karib Ki Ageng Pemanahan—yang kelak dikenal sebagai patih pertama Kasultanan Mataram Islam.
Pasarean mewedarkan sasmita tentang bagaimana kaidah nguri-uri (melestarikan), merawat, mengambil hikmah, bahkan membaca simbol-simbol budaya leluhur kita.
Dari sebuah makam, masa lalu memendar dan pantas kita rekam.