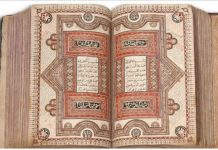Di beberapa tempat ketika saya plesiran ke sebuah daerah, saya sering kali mendapati pemandangan yang cukup aneh. Keanehan ini mungkin bersifat subjektif, sering kali saya mendapati sebuah banner segi panjang membentang di tepi jalan, di tepian sungai dan di pelbagai tempat-tempat lainnya. Banner tersebut bertuliskan huruf kapital dan menyerukan ajakan yang bijak.
Kira-kira kalimat yang ada di banner tersebut berbunyi seperti ini, “JANGAN BUANG SAMPAH DI SINI”. Naasnya, seruan itu tidak digubris bahkan bertolak dari makna persuasifnya. Terlihat sampah masih berceceran di sekitar banner tersebut. Sangat aneh bukan? Himbauan yang jelas-jelas terpampang dengan tegas, tidak mampu dan tidak cukup ampuh untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam hal membuang sampah.
Menurut saya pribadi, inilah pemandangan aneh yang sering saya jumpai.
Belakangan, saya tersadar jika perilaku masyarakat bawah yang sering membuang sampah sembarangan ini sesuatu yang lumrah.
Bagaimana tidak, orang yang punya kedudukan tertinggi di republik ini saja menyamakan tanaman sawit sebagai tanaman hutan alam. Bahkan, mendukung pembabatan hutan (deforestasi) untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.
Perilaku para teknokrat merupakan manifestasi dari perilaku masyarakatnya. Mungkin tesis ini menjadi jawaban kenapa masyarakat akar rumput sulit untuk diajak berperilaku pro-lingkungan. Saya meyakini, sumber utamanya adalah praktik public policy yang buruk dari para pemimpin negeri.
Baca juga: Mitos Menjembatani Tradisi dan Pemahaman Modern (1)
Setiap tahunnya, pemerintah menambah area deforestasi dengan dalih menggenjot pertumbuhan ekonomi. Tak sedikit pula pemerintah sering berkamuflase dan berlindung dengan nama PSN (Program Strategis Nasional).
Sehingga, sering kali pemerintah maupun pihak swasta menghalalkan berbagai cara untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari eksploitasi alam. Globalforestwatch.org, merilis data yang cukup memprihatinkan, Sejak tahun 2001 hingga 2023, Indonesia kehilangan 30.8 Mha tutupan pohon, setara dengan penurunan 19% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 22.2 Gt emisi CO₂e.
Lalu, sejak tahun 2001 sampai 2023, Indonesia kehilangan 85% tutupan pohon terjadi di berbagai wilayah, di mana pendorong kehilangan yang dominan mengakibatkan deforestasi.
Kita semua perlu menghela nafas yang dalam dan mengernyitkan dahi ketika membaca laporan fwi.or.id, bahwa pemerintah Indonesia merencanakan deforestasi atau penggundulan hutan seluas 325.000 ha per tahun hingga 2030. Angka ini terdapat dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pemerintah yang dikirimkan ke PBB pada akhir Juli 2021.
Dampak nyata dari deforestasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah hilangnya hutan-hutan adat di Indonesia. Masyarakat adat yang sebelumnya mensakralkan hutan karena bagian dari nilai luhur dari alam, kini harus menelan pil pahit. Mereka kehilangan mata pencahariannya, bahkan terancam keberlangsungan hidupnya karena kehidupan mereka banyak ditopang oleh hutan.
Beberapa hutan adat yang terancam dan hilang adalah Hutan Adat di Seruyan, Kalimantan Tengah. Hilang karena diganti dengan perkebunan sawit, menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan nyawa warga. Hutan Adat di Boven Digoel, Papua Selatan, beberapa hektar hutan milik Masyarakat Adat Wambon Tekamerop di Distrik Subur telah rata dengan tanah.
Hutan Adat Suku Awyu di Papua, terancam hilang menjadi perkebunan dan pabrik kelapa sawit oleh konsesi gelap perusahaan cangkang Malaysia.
Masyarakat Adat Long Isun di Kalimantan Timur, masih berjuang melawan pembalakan dan pembangunan industri sawit di wilayah adatnya.
Hutan Adat Warbon, lebih dari 40 tahun berhadapan dengan LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang mengklaim sebagian lahan hutan adat tersebut sebagai lahannya.
Mitos, Ekologi, dan Manusia
Banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berkedok ramah lingkungan, sudah memenuhi syarat ketahanan ekologis dan akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai konsesinya. Mereka juga sering berdalih bahwa pembangunan yang dilakukan sudah dikaji sesuai kaidah ilmiah. Sehingga mereka acap kali beretorika segala sesuatunya sudah dipertimbangkan dengan matang.
Praktik di lapangan, retorika-retorika tersebut hanya bualan semata. Tak jarang pula mereka tidak mengindahkan adat istiadat yang sudah terpatri di masyarakat. Mereka berkelak bahwa pemahaman masyarakat irasional dalam memperlakukan alam, tidak saintifik dan tidak konkrit dalam menjaga ekologi.
Dampaknya, nilai-nilai kultural masyarakat dinilai hanya mitos yang tak berdasar. Padahal, perilaku mereka lah yang serampangan dalam memperlakukan alam. Perkembangan mitos pada masyarakat adat maupun masyarakat lain lebih syarat terhadap ketahanan ekologis dibanding proyek yang terkesan saintifik tetapi sangat tidak ramah terhadap keberlanjutan ekologi.
Antara mitos dan ekologi adalah dua konsep yang tampak bertolak belakang, namun sebenarnya saling terkait dalam cara manusia memahami dan berinteraksi dengan alam.
Pemahaman mitos sebagai narasi simbolis yang sering diwariskan secara turun-temurun, tidak hanya berfungsi sebagai cerita penghibur, tetapi juga sebagai cara untuk menjelaskan fenomena alam, menetapkan norma sosial, dan membangun hubungan spiritual dengan lingkungan.
Sementara itu, ekologi, sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya, menawarkan pemahaman ilmiah tentang keseimbangan alam. Mitos telah lama menjadi alat untuk memahami alam. Dalam bukunya The Power of Myth (1988), Joseph Campbell, secara ciamik menjelaskan bahwa mitos adalah “kisah suci” yang membantu manusia menghadapi misteri kehidupan, termasuk fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, atau perubahan musim.
Mitos yang berkembang di masyarakat adat maupun masyarakat lain lebih efisien terhadap ketahanan ekologis dibanding proyek yang terkesan saintifik tetapi sangat tidak ramah terhadap keberlanjutan ekologi
Misalnya, dalam mitologi Yunani, Demeter, dewi pertanian, dikaitkan dengan siklus musim dan kesuburan tanah. Kisahnya mencerminkan ketergantungan manusia pada alam untuk bertahan hidup. Mitos telah menawarkan pemahaman simbolis tentang alam, ekologi memberikan penjelasan ilmiah.
Namun, kedua pendekatan ini tidak selalu bertentangan. Mencermati buku The Ecology of Wisdom (2008), Arne Naess, seorang filsuf lingkungan, memperkenalkan konsep ekologi dalam deep ecology yang menekankan kesatuan manusia dengan alam. Naess mengakui bahwa banyak mitos dan kepercayaan tradisional telah lama mempromosikan pandangan ini, jauh sebelum ilmu ekologi modern muncul.
Naess mencontohkan, dalam mitologi Hindu, konsep Vasudhaiva Kutumbakam (seluruh dunia adalah satu keluarga) mencerminkan prinsip ekologi bahwa semua makhluk hidup saling terhubung. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran ekologis modern yang menekankan pentingnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
Mitos dan Kearifan Lokal Keindonesiaan
Di Indonesia, bertabur banyak narasi mitos yang beririsan dengan ketahanan ekologis. Beberapa lawatan saya ke beberapa daerah secara empiris menyaksikan keampuhan mitos dalam mengendalikan ketahanan ekologi dan pelestarian alam. Secara turun temurun, kearifan lokal tersebut terus dirawat dan dipraktikkan.
Di Kudus, misalnya, Di Dukuh Masin, Desa Kandangmas, Kecamatan Jekulo, terdapat sebuah makam yang diyakini masyarakat sebagai makam Dewi Nawangsih, di mana tokoh ini juga diyakini sebagai salah satu anak dari Sunan Muria. Kawasan makam Dewi Nawangsih secara turun temurun disakralkan oleh masyarakat setempat.
Bahwa, siapapun tidak diperbolehkan membawa sekecil apapun dari bagian pohon-pohon yang tumbuh di kawasan makam. Sekalipun hanya daun atau ranting sekecil apapun. Sehingga di kawasan ini, kita akan menjumpai banyak pohon jati yang berumur puluhan sampai ratusan tahun masih gagah berdiri.
Baca juga: Ulama di Indonesia: Popularitas, Kemewahan dan Alat Penguasa
Bahkan, jika ada pohon jati yang tumbang karena termakan usia, haram pula hukumnya untuk diambil dan dikeluarkan dari kawasan Makam Dewi Nawangsih.
Kesakralan terhadap lingkungan tersebut dilatarbelakangi kepercayaan yang magis. Mitos berasal dari historis antara ketegangan Sunan Muria dengan putrinya Dewi Nawangsih beserta Raden Rinangku, santri dari Sunan Muria. Pohon-Pohon yang berdiri saat ini diyakini masyarakat merupakan buah sabdaan dari Sunan Muria.
Sang Sunan tidak merestui jalinan asmara yang dijalin oleh Dewi Nawangsih dan Raden Rinangku. Singkat cerita, Raden Rinangku dipanah oleh Sunan Muria. Melihat kekasihnya menghela nafas terakhir, Dewi Nawangsih memilih menancapkan panah yang ada ditubuh Raden Rinangku untuk ikut mengakhiri hayat.
Melihat anaknya ikut meninggal, Sunan Muria diceritakan murka, sehingga meluapkan amarahnya dengan mengutuk orang-orang yang ikut melihat peristiwa menyedihkan itu menjadi pohon jati.
Sabdaan dimaksudkan karena Sunan Muria menyayangkan orang-orang yang ada di sekitaran peristiwa seharusnya bisa mencegah perbuatan Dewi Nawangsih. Tetapi mereka mimih hanya diam tak melakukan apa-apa. Hal itu yang memantik Sunan Muria mengutuk orang-orang tersebut menjadi sebatang pohon jati.
Masih di kawasan Sunan Muria, berkembang pula sebuah mitos yang tak kalah magis. Yaitu, tentang macan putih sebagai hewan tunggangan Sunan Muria di masa lalu. Masyarakat meyakini macan putih tersebut sampai sekarang ini masih hidup. Hutan di belakang kompleks makam Sunan Muria menjadi hunian utamanya.
Dari mitos tersebut yang menggerakkan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam di Kawasan Pegunungan Muria. Bahkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, terdapat organisasi masyarakat yang secara khusus bergerak di bidang konservasi lingkungan. Jargon yang selalu digaungkan adalah “Hutan adalah amanah. Menjaganya adalah Ibadah”.
Sunan Muria menjadi simbol utama gerakkan mereka. Bahwa mereka meyakini Hutan Muria menjadi bagian warisan yang ditinggalkan Sunan Muria, sehingga segala cerita-cerita yang bernuansa tentangnya patut untuk diimplementasikan dan dikontekstualisasikan ke dalam laku keseharian.
Mitos dan Krisis Ekologis Modern
Di era krisis ekologis seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi sekarang ini, meninjau ulang narasi mitos sangat diperlukan. Mitos dapat menjadi alat yang powerful untuk membangkitkan kesadaran lingkungan. Meminjam ulasan Robin Wall Kimmerer, seorang ahli biologi dan anggota suku Potawatomi, dalam bukunya Braiding Sweetgrass (2013), menggabungkan ilmu ekologi dengan kearifan tradisional.
Ia menceritakan bagaimana mitos dan cerita rakyat suku asli Amerika mengajarkan penghormatan terhadap alam dan tanggung jawab untuk merawatnya. Kimmerer berargumen bahwa mitos bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi dapat menjadi panduan untuk masa depan.
Misalnya, mitos tentang Pohon Kehidupan yang ditemukan dalam berbagai budaya, dari Norse hingga Mesir kuno ini dapat menginspirasi upaya reboisasi dan konservasi hutan di era modern.
Muhammad Fiam Setyawan melalui tulisannya yang terangkum dalam kolom ulasan damarku.id, Yang Rusak dan Mengalami Desakralisasi (2025) memberikan paradigma yang menarik tentang buku Antara Tuhan, Manusia, dan Alam, karya Seyyed Hossein Nasr, bahwa sains modern perlu ditinjau ulang, utamanya memudarnya metafisika dalam kajian sains modern membuat alam kehilangan sisi simbolisme spiritual.
Alam hanya menjadi objek kajian logis dan empiris, berbanding terbalik dengan metafisika yang mengajak manusia untuk memahami alam secara intuitif. Tinjauan kritis terhadap sains modern tersebut memantik seberapa jauh dapat menekan persoalan krisis ekologi sekarang ini.
Dengan meminjam mitos sebenarnya menjadi alternatif yang patut untuk diuji cobakan. Melalui narasi-naris mitos masyarakat di masa lalu, dapat digunakan sebagai pendekatan dalam konservasi modern.
Program konservasi berbasis budaya lokal yang menggabungkan mitos dan kearifan tradisional telah diterapkan di beberapa tempat, seperti di kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah.
Demikian pula, mitos Hutan Larangan di beberapa suku di Indonesia menjaga keutuhan kawasan hutan tertentu dengan mengaitkannya pada kepercayaan mistis.
Beberapa mitos juga menempatkan hewan tertentu sebagai makhluk suci atau pelindung. Misalnya, masyarakat Dayak memiliki mitos tentang burung Enggang yang dianggap sebagai simbol roh leluhur. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk tidak memburu burung tersebut, yang secara tidak langsung melestarikan populasinya.
Kemudian budaya Bali, mitos tentang Dewi Danu mengajarkan pentingnya menjaga danau serta sumber mata air sebagai bagian dari keseimbangan alam. Sistem subak dalam pertanian Bali juga didasarkan pada konsep harmonisasi dengan alam, yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan mitologi setempat.
Di tengah derasnya arus sains, apakah ada skema yang mampu menggerakkan secara kolektif masyarakat untuk patuh dan berperilaku seperti nilai-nilai luhur yang sering dianggap mitos di atas? Tidak perlu dijawab, kita hanya bisa merefleksikannya dan melihat kondisi senyatanya yang terjadi di negeri ini.
Tantangan dan Elaborasi
Mitos memiliki potensi besar untuk mendukung kesadaran ekologis, pekerjaan rumahnya, ada tantangan dalam mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan modern. Tom Wessels melakukan catatan kritis yang termuat dalam The Myth of Progress (2006).
Tom Wessels mengkritik pandangan antroposentris yang menganggap manusia sebagai pusat alam semesta. Ia menyarankan agar kita belajar dari mitos-mitos tradisional yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya.
Mitos dan ekologi, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami dan merawat alam. Mitos bukan hanya cerita kuno, tetapi juga sumber kearifan yang relevan dengan tantangan ekologis modern. Dengan menggabungkan pemahaman mitologis dan ilmiah, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan alam dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
Baca juga: Yang Rusak dan Mengalami Desakralisasi
Elaborasi mitos dan nuansa ilmiah patut untuk diuji cobakan. Misalnya, kira-kira bentangan banner yang berisi ajakan persuasif untuk tidak menebang pohon atau tidak membuang sampah sembarangan, apakah akan lebih ampuh dibanding ketika mengampanyekan konservasi alam dengan menggunakan atribut yang sedikit mistis yaitu, membaluti pohon dengan kain lurik atau kain bali. Bisa juga menaruh dupa dan kemenyan di tempat yang sering dilanggar masyarakat dalam membuang sampah sembarangan.
Kira-kira eksperimen tersebut mana yang dapat mengendalikan perilaku masyarakat? Peluangnya lebih besar mana masyarakat akan tunduk terhadap himbauan untuk berperilaku pro-lingkungan? Keduanya memiliki peluang yang sama.
Tapi pada kenyataanya bentangan banner hanya jadi jargon semata. Sedangkan atribut-atribut yang dianggap mistis itu mampu menundukkan perilaku mencemari lingkungan. Akan tetapi, Eksperimen tersebut hanya berlaku dan diperuntukkan masyarakat akar rumput saja. Jangan diuji cobakan pula ke para teknokrat atau pengampu kebijakan (pemerintah). Sudah bisa dipastikan akan gagal dan sia-sia.
Almarhum, Salim Said, seorang Guru Besar sekaligus Pengamat Politik, sudah mengingatkan, “kenapa negeri ini tidak maju? karena Tuhan saja tidak ditakuti para politisi”. Apalagi mitos yang mungkin sama sekali tidak dipertimbangkan keberadaannya oleh mereka para pengampu kebijakan.
Mengutip pernyataan Robin Wall Kimmerer, perlu untuk direfleksikan bersama bahwa, dalam setiap mitos, ada benih kebenaran yang menunggu untuk ditanam kembali di tanah subur kesadaran kita. Dengan merawat benih-benih ini, kita dapat menumbuhkan dunia yang lebih hijau dan lebih bijaksana.