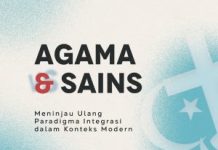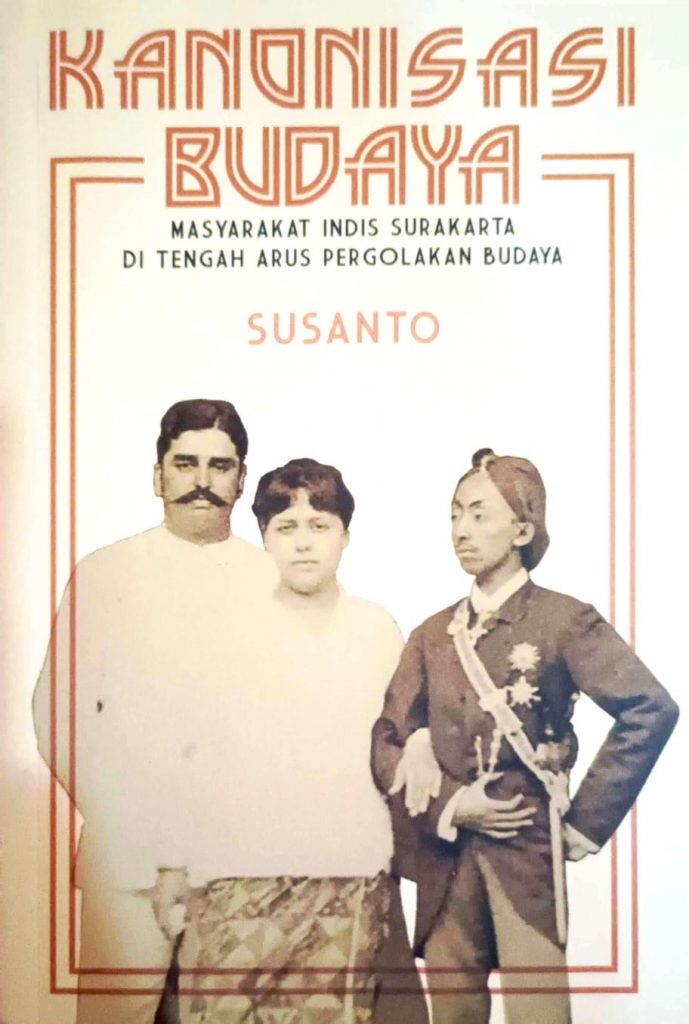
Brook Hetlen sempat menulis surat kepada Andy Dufrense, begini bunyinya, “dunia bertumbuh, dan jadi tergesah gesah”. Surat yang dilayangkan Brook Hetlen ini ada dalam adegan film Shawshank Redemption (1994).
Kalimat Brook Hetlen ini senada dengan gambaran kota Surakarta pada awal abad ke-18. Melalui politik identitas yang mengukuhkan sekat antargolongan yang dilakukan oleh pihak VOC, Surakarta bertumbuh, surakarta menghadapi modernitas.
Dalam hal ini modernitas di Surakarta sesuai dengan kesan Takashi Sirahisi (2022). Modernitas di Hindia Belanda mengesankan pembaratan. Melalui buku Kanonisasi Budaya, Susanto memperjelas kesan pembaratan, sekaligus menceritakan bagaimana pergolakan budaya Indis di tengah masyarakat Surakarta yang majemuk.
Surakarta sebelum tergesah bertransformasi menjadi metropolis hanyalah desa kecil di tepian Sungai Bengawan Solo. Pemilihan Surakarta sebagai ibukota baru Mataram Islam sejak runtuhnya Kartasura pasca geger pecinan tak lepas dari campur tangan VOC.
Pada waktu itu, VOC sedang memulai pembangunan benteng Grootmodigheit atau sekarang Vestenburg. Melalui kebijakan Daendels yang mengintegrasikan wilayah antarsatu pos dengan pos yang lain—dalam konteks ini Semarang dan Surakarta. Dari sinilah Surakarta menjadi magnet bagi berbagai Etnis-Eropa, China, Arab, dan seterusnya untuk singgah dan kemudian menetap.
Baca juga: Janturan: Ruang dan Pesan
Susanto mengajak pembaca untuk menelisik ulang kehidupan sosio-kultural di Surakarta akibat munculnya berbagai komunitas tersebut. “keberadaan komunitas non-Pribumi terutama Eropa secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk modernisasi kota di Surakarta”.
Selain itu, melalui perubahan sistem dari pemerintahan Hindia Belanda menjadi Rebublik Bataaf, Daendels mulai mempreteli hegemoni raja-raja Jawa melalui sistem demokrasinya.
Kuasa dan otoritas raja-raja Jawa, yang mulanya menjadi titik sentral kosmologis, perlahan-lahan runtuh. Inilah pijakan awal di mulainya dejawanisasi yang dilakukan oleh Belanda.
Hegemoni bangsa kulit putih berlanjut dengan adanya kebijakan ekonomi baru pada masa pemerintahan Raffles.
Pada masa ini liberalisasi ekonomi dilakukan, sehingga banyak pelaku ekonomi baru non-pribumi khusunya Eropa. Ditambah dengan adanya akses ke Semarang dan Surabaya, semakin mempermudah akses masuknya barang-barang yang bernilai jual dari luar Surakarta.
Hal ini kemudian memunculkan gaya hidup baru bagi masyarakat Surakarta. Mulai dari fashion dengan munculnya beskap langgerharjan, transportasi dengan munculnya jalur Surakarta-Semarang, hingga trem yang menghubungkan dari satu wilayah ke wilayah lain di Surakarta, hotel yang menarik datangnya wisatawan, modernisasi di bidang militer legion mangkoenegaran, hingga Taman Hiburan Rakyat Sriwedari. Praktik kanonisasi mengubah surakarta menjadi kota tanpa tidur.
Lebih lanjut, Susanto mengungkai kanonisasi ini tak hanya merambah bidang ekonomi-politik saja, perundang-undangan misalnya. Belanda mulai menggeser sistem peradilan lokal pada 1903 dan menggantinya dengan produk hukum Belanda.
Di bidang pendidikan mulai diberlakukan aturan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar sekolah. Tentu ini menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat Surakarta yang notabene mayoritas berbahasa Belanda.
Di luar hukum, pendidikan dan fashion, campur tangan Belanda juga tampak pada upacara istana. Belanda memunculkan perubahan radikal hingga menurunkan kewibawaan penguasa-penguasa di wilayah vorstenlanden kala itu.
“Kebijakan Eropanisasi ini akhirnya melahirkan masyarakat dikotomi rasial yang menimbulkan kegelisahan terutama bagi komunitas indo dan pribumi jawa di Surakarta”. Kebijakan tersebut-sebut kemudian menimbulkan gejolak di antara penduduk non-Eropa dan pendatang Eropa. Keduanya saling berebut eksistensi dan identitas mereka.
Surakarta pun berkembang, tak hanya menjadi episentrum kebudayaan, tetapi juga episentrum pergerakan. Pelbagai komunitas yang merasa gelisah memberikan perlawanan terhadap praktik kanonisasi yang terus saja berlanjut. Melalui insulinde kaum Indo melakukan perlawananya.
Disusul kemudian komunitas Islam yang diwakili para elite Jawa, yang diprakarsai oleh Samanhudi, mereka pun membentuk satu perkumpulan yang terdiri dari pedagang batik Laweyan yakni Sarekat Dagang Islam. Kelompok satu ini kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI). Di wadah inilah tak hanya elite Jawa yang masuk menjadi anggota, tetapi juga bangsawan keraton mulai menaruh hati dengannya.
Baca juga: Akulturasi Islam-Jawa: Sedekah Bumi, Kesenian, Kirab Budaya
Klimaksnya terjadi pada kongres kebudayaan tahun 1929 yang menjadi tonggak kembalinya eksistensi budaya lokal yang tergerus akibat kanonisasi. “Seusai kongres muncul gejala harmoni dalam hubungan kehidupan sosio-kultural di Surakarta”. Selain itu harmonisasi ini juga diakibatkan krisis ekonomi yang mengguncang Hindia Belanda akibat terjadinya malaise juga akibat dari invasi Jerman ke Belanda pada 1940.
“Dalam menghadapi krisis dan tekanan politik, di Surakarta muncul aktivitas yang cenderung berorientasi pada kebudayan”. Dalam proses ini Jawanisasi mengalami peningkatan berjalan lurus dengan kesadaran semua elemen kelompok yang sadar akan kemajemukan. Pada titik ini semua tersadar akan titik temu antara silang budaya Timur dan Barat.
Untuk mempertegas hal ini muncul zelfbestuursregelen yang mempertegas kuasa raja Jawa atas daerah yang diperintahnya. “Sejak saat itu pula surakarta tampak sebagai bentuk tatanan sosio-kultural baru yang bersifat majemuk dengan identitas budaya Jawa Surakarta yang menonjol”.
Judul Buku: Kanonisasi Budaya: Masyarakat Indis Surakarta di Tengah Arus Pergolakan Budaya
Penulis: Susanto
Penerbit: Selaklali
Cetakan: Pertama, Juni 2023
Tebal: xvii + 308 hlm
ISBN: 978-623-09-3284-7