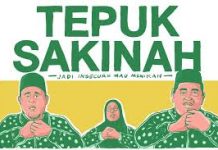Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) lewat surat ketetapan (SK) nomor 012/LF-PBNU/II/2023 mengumumkan 1 Sya’ban 1444 H jatuh pada Rabu Wage, 22 Februari 2023 M.
Ketetapan ini diputuskan atas dasar Istikmal setelah penyelenggaraan rukyatul hilal pada Senin Pahing 20 Februari 2023. Bulan Sya’ban atau yang orang Jawa sebut sasi ruwah merupakan bulan yang penting sebelum menyambut sasi poso atau bulan ramadhan. Dalam alam spiritualitas masyarakat Jawa, ruwah mempunyai esensi filosofis yang tinggi.
Ruwah sendiri berasal dari frasa “Arwahi” atau Ruh. Dengan kata lain sasi ruwah mempunyai arti yaitu mempersiapkan ruh, menyucikan hati sekaligus membersihkan kalbun dari berbagai penyakit hati yang bakal mengganggu ibadah di sasi poso.
Jadi, sasi ruwah mempunyai piwulangan (nasihat) agar orang Jawa mempersiapkan kondisi batinniyah yang bersih dan lepas dari penyakit iri, dengki, dan segala tindakan yang membuat diri maupun orang lain merugi. Ruwah dan ritus sebelum ramadhan dilakukan agar setiap insan mampu khusyuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan suci.
Laku ini sama persis dengan ajaran tasawuf akhlaki Imam Al-Ghazali yang dalam kitab Al-Munqidz Min al-Dlalal menjelaskan bahwa, “pensucian hati merupakan gerbang awal dalam laku Suluk seorang Salik yang menempuh jalan Tarekat”. Laku ini lebih menekankan aspek kerohanian dengan menyucikan hati atas hal apa pun selain Allah.
Sekilas, esensi dari piwulangan sasi ruwah dan ajaran tasawuf akhlaki Imam Al-Ghazali sama walau beda konteks tujuan atau muara dari laku-laku tersebut. Yang satu hendak mempersiapkan diri guna menyambut bulan suci Ramadhan, sedangkan yang kedua merupakan laku perjalanan ruhaniyah dari penghayatan kasyaf sampai memuncak di makrifatullah.
Laku kebudayaan di sasi ruwah ini tampaknya sudah ada sejak era dakwah Walisanga. Tradisi ruwah biasanya dilakukan di kampung pasarean di suatu tempat. Tradisi ini diadaptasi oleh para dewan wali sebagai sintesis dua kebudayaan besar antara Islam dan Jawa.
Baca juga: Pendidikan di Kerajaan Langkat
Jauh sebelum Islam bahkan Hindu-Buddha dating, masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan tinggi pada roh para leluhur maupun benda-benda yang dianggap keramat. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa Gunung, Air, dan Pohon merupakan titik spiritual penting dalam nalar kerohanian mereka.
Di pasareanlah, dua kebudayaan besar ini bertemu dalam satu tarikan napas, yang satu percaya akan roh leluhur yang sudah pergi mendahului ditambah dengan instrumen pepohonan yang dianggap punya energi (sebab makam kuno masa lampau pasti terdapat pepohonan; kepoh, beringin, randhu alas).
Sedang yang berikutnya meyakini bahwa pasarean merupakan muara dari kehidupan di dunia sekaligus jadi pengingat asal-muasal tujuan kehidupan (sangkan paraning dumadi).
pasarean merupakan muara dari kehidupan di dunia sekaligus jadi pengingat asal-muasal tujuan kehidupan (sangkan paraning dumadi).
Berangkat dari latar belakang tersebut, dewan wali tempo itu memiliki strategi dakwah pendekatan budaya, sebab para wali sadar tataran kosmos yang sudah mengakar dalam sendi masyarakat Jawa tak harus dicerabut begitu saja.
Islam tidak mengalami pertentangan dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Bahkan Islam mampu menyisipkan ajarannya dalam setiap laku kebudayaan orang Jawa.
Pendekatan ini dikatakan Simuh sebagai pendekatan kompromis atau akomodatif, yakni sebuah pendekatan yang dijalankan oleh para wali dan guru-guru tarekat yang tidak mempersoalkan kemurnian agama, Islam bisa diterima berdampingan dengan tradisi lama tanpa menimbulkan ketegangan berarti.
Institusi-institusi tradisi lama seperti kenduri dan upacara-upacara lainnya bisa di-Islam-kan dengan mudah. Pendekatan ini dilakukan para wali atau sufi untuk menyusupkan unsur-unsur Islam tanpa harus mengorbankan filsafat dan seni budaya terdahulu (Simuh, 2016: 25).
Senada dengan Simuh, sejarawan asal Skotlandia, H.A.R Gibb, mengatakan keberhasilan metode dakwah yang adaptif serta bersifat antikonfrontatif dalam penyebaran Islam di Jawa merupakan keberhasilan paling menakjubkan di Asia Tenggara. Dengan kata lain, upaya preventif yakni menggunakan metode asimilasi dan akulturasi budaya menjadi perantara keberhasilan Islamisasi di Jawa.
Tradisi Sadranan-Padusan
Koentjaraningrat dalam Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (1986) menyebut setidaknya kebudayaan mempunyai tiga unsur. Pertama, kebudayaan sebagai wujud ideal yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu bentuk kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dsb.
Kedua, kebudayaan sebagai wujud perilaku, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat.
Ketiga, kebudayaan sebagai wujud benda, yakni sebuah kebudayaan dengan hasil material dengan tanda-tanda hasil karya. Kali ini penulis akan menyajikan wujud kedua yaitu kebudayaan dengan wujud perilaku, sebuah wujud yang sering dilakukan terus menerus dan mentradisi dalam tonggak kebudayaan masyarakat Jawa-Islam.
Sasi ruwah atau yang di penanggalan Hijriyah dinamai bulan Sya’ban, mempunyai produk kebudayaan berupa Sadranan—orang Jawa lazim menyebutnya dengan nyadran atau nyekar.
Di sini pasarean jadi titik sentral. Kemudian pada tanggal yang sudah disepakati, orang-orang akan datang berbondong-bondong lengkap dengan sanak-keluarganya di pasarean membawa uborampe untuk keperluan kenduri yang menjadi inti tradisi.
Pasarean dipilih sebab tempat ini merupakan salah satu dari tujuh ajaran tentang Sapta Mandala Srawung, yaitu konsepsi tentang ruang publik orang Jawa sebagai tempat pergumulan sosial budaya. Ajaran ini dicetuskan oleh Patih pertama Kasultanan Mataram Islam, Ki Juru Martani atau Tumenggung Mandaraka (M. Yaser Arafat, 2021: xxii).
Dari pasarean juga terdapat kawruh (ilmu) tentang kehidupan. Perihal bagaimana kehidupan di dunia merupakan tempat sementara (urip mung mampir ngombe) dan kematian-pasarean merupakan gerbang utama menuju alam keabadian.
Sadranan atau nyadran atau nyekar merupakan aktivitas ziarah kubur dengan menaburi bunga setaman di atas kijing atas jirat makam. Namun, frasa nyekar mempunyai makna yang lebih luas dan tak hanya dimaknai sebagai aktivitas menabur bunga. Lebih jauh, nyekar mempunyai esensi menaburi roh leluhur yang sudah berpulang dengan merapal doa-doa baik dan tulus.
Bahkan dalam kehidupan keseharian di sasi-sasi berikutnya setelah Ruwah. Orang Jawa yang hendak ziarah di suatu pasarean masih menyebut kegiatan ini dengan istilah nyadran “ameh nyadran sik ning sarean,” mau berziarah dulu di pemakaman. Tampaknya, tradisi ini mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat Jawa.
Istilah nyadran yang biasanya hanya dipakai ketika menyambut tradisi sadranan di sasi ruwah bergeser makna menjadi aktivitas ziarah di kehidupan sehari-hari.
Sadranan sendiri merupakan tradisi yang cukup kompleks. Sadranan atau nyadran merupakan aktivitas yang dilakukan sebelum menyambut sasi Poso. Tradisi ini biasa dilakukan di kampung-kampung pasarean masyarakat sekitar.
Seperangkat tradisi sadranan berupa kenduri/kenduren/kondangan yaitu sebuah ritual pembacaan doa-doa (umbul dunga) yang dipimpin seorang tokoh agama, kiai, atau modin setempat. Selain itu, juga ada uborampe/berkatan yang diwadahi sebuah besek/tampah/tenongan/ceting (wadah makanan tradisional dari ayaman bambu) yang berisi nasi, ingkung ayam, sayur semur, ketan, apem, kholak, pisang dan janur (daun kelapa muda).
Perangkat yang terakhir yaitu besik makam, sebuah kegiatan membersihkan seluruh pasarean bersama-sama. Di beberapa tempat kegiatan besik makam ini dilakukan satu hari sebelum sadranan dilaksanakan.
Baca juga: Tiga Aspek Tasawuf dalam Sadranan
Tradisi ini diawali dengan pembacaan dzikir yasin wa tahlil yang dipimpin kiai. Sebelum doa-doa dilangitkan, biasanya orang-orang yang mengikuti tradisi ini akan menuliskan nama-nama leluhur yang sudah berpulang ke Rahmatullah supaya ikut didoakan.
Uniknya, uborampe yang sudah disiapkan ditata rapi di tengah-tengah dan diputari jamaah tradisi ini, melingkar. Namun, formasi ini tidak paten, di beberapa daerah kadang susunan formasi memanjang horizontal dan mengular. Uborampe juga didoakan agar mendapat berkah dari setiap makanan yang nanti disantap bersama-sama.
Formasi melingkar ini tidak paten, di beberapa daerah kadang memanjang horizontal dan mengular.
Setelah upacara kenduri selesai, orang-orang makan bareng dan saling tukar-menukar makanan yang sudah dibawa. Unsur kebersamaan, semangat persatuan dan persaudaraan kental dalam tradisi ini. Orang-orang yang jarang bertemu tiba-tiba dapat bersilaturahmi.
Rentetan kegiatan selanjutnya yaitu besik makam. Kegiatan ini berupa membersihkan lokasi pasarean yang dinilai kotor, angker, terbengkalai dan kurang enak di pandang untuk dibersihkan atau ditata sedemikian rupa. Di beberapa daerah kegiatan ini bisa dilaksanakan sebelum tradisi ini dilaksanakan maupun sesudah kenduri dan adat makan uborampe.
Selain tradisi sadranan yang umum dikenal masyarakat di Jawa (khususnya bagian tengah dan timur) terdapat salah satu tradisi yang ada di daerah Vorstenlanden (daerah raja-raja) yaitu tradisi padusan. Sebuah tradisi bersih diri atau bersuci menyambut sasi Poso.
Padusan berasal dari kata “adus” yang artinya mandi, dengan imbuhan “pe” dan “an” istilah ini dalam kaidah fonetis lidah orang Jawa dilafalkan menjadi padusan. Padusan mempunyai piwulangan yakni sebagai sebuah kegiatan membersihkan jasad atau badan (lahiriyah) dari segala najis besar dan kecil, agar sebelum menyambut sasi Poso orang Jawa sudah dalam keadaan yang suci lahiriyah dan siap menyambut serta melaksanakan amalan-amalan di bulan suci.
Padusan sendiri merupakan ritus yang masih dijaga orang-orang di daerah Vorstenlanden atau daerah eks-karesidenan Surakarta (Soloraya). Tradisi ini biasanya dilakukan di umbul (sumber mata air). Kegiatannya berupa berenang atau sekadar ciblon-keceh (bermain air) di sekitar umbul.
Di wilayah Soloraya sendiri lokasi umbul cukup banyak ditemukan, misalnya di daerah Boyolali, terdapat umbul sungsang, umbul winwin, umbul langse, dsb. Sementara itu, di daerah Klaten tepatnya di kecamatan Tulung juga banyak dijumpai umbul mata air; umbul cokro, umbul nilo, umbul ponggok, umbul manten, umbul pelem, dsb.
Dari sadranan-padusan terdapat sasmita bahwa tradisi berbasis lokalitas punya esensi ajaran kebudayaan yang sarat nasihat. Sebagai contoh perihal uborampe, bahwa ingkung merupakan interpretasi dari manekung, yakni sebuah ajaran laku samadi/meditasi dalam ilmu tasawuf yang kemudian dimanifestasikan sebuah usaha dzikir kepada Allah dengan kesungguhan hati.
Adapula ketan interpretasi dari khoto’an, merupakan perlambang kesalahan pada diri manusia. Kemudian apem berasal dari kata afun yakni sebuah simbol pengampunan. Adapun kholak merupakan interpretasi dari sang Khaliq sebagai Tuhan seluruh alam. Selain itu, juga terdapat janur sebuah interpretasi dari jaa’nur merupakan simbol dari cahaya illahi.
Tradisi Ruwah dan ritus sebelum Ramadhan yang dilaksanakan di pemakaman ini, niscaya meruntuhkan frame pasarean yang belakangan dikonstruksi sebagai tempat yang angker dan penuh hal negatif.
Kebudayaan yang mencakup bentuk fisik dan non-fisik adalah sebuah kawruh tentang kehidupan yang sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun lalu.