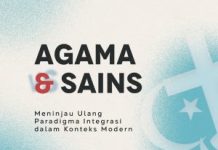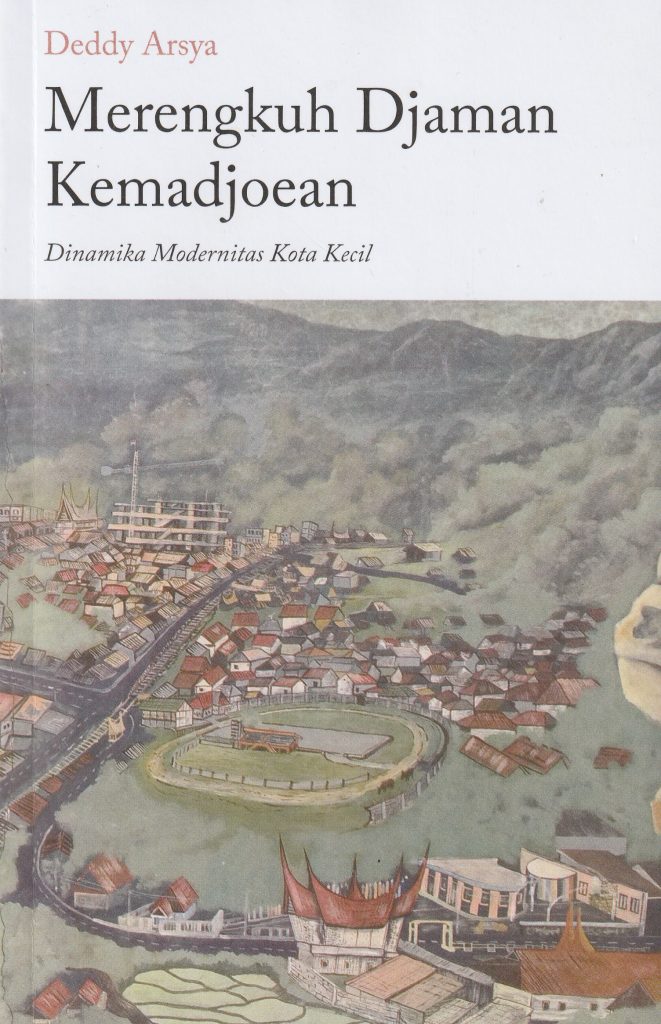
Buku ini membentangkan bagaimana proses pembaratan sebuah kota kecil bernama Padang Panjang. Sebuah terpaan modernitas di dataran tinggi suku Minangkabau. Cahaya “Barat” itu lamat-lamat menderas, menghujam ulu jantung pedalaman Sumatera.
Modernitas adalah efek dari serangkaian proses modernisasi. Dampak dari embusan modernitas yang mendayu-merayu ini bukan hanya melahirkan pencangkokan budaya, tetapi tak jarang melahirkan modernitas palsu.
Sederet konsekuensi negatif dari modernitas membuat masyarakat menjumpai kondisi paradoksal, tatanan yang membingungkan—bukan hanya urusan simbolik—sampai ketidakselarasan sosial. Kondisi semacam inilah yang dialami penduduk nun di tengah Sumatera.
Deddy Arsya cukup jeli dan tekun mengolah data dari masa silam. Pelbagai referensi digunakan sebagai pijakan bercerita modernitas, mulai dari teks-teks sastra, folklor setempat, catatan perjalanan, biografi, memoar, koran, sampai terbitan berkala. Kekayaan ini niscaya membuat pembaca diajak berkeliling dari satu pengalaman ke pengalaman lain, yang sempat dirasakan oleh person dan masyarakat secara kolektif di masa lalu.
Deddy Arsya cukup jeli dan tekun mengolah data dari masa silam. Pelbagai referensi digunakan sebagai pijakan bercerita modernitas, mulai dari teks-teks sastra, folklor setempat, catatan perjalanan, biografi, memoar, koran, sampai terbitan berkala
Studi sejarah ala Rudolf Mrazek ini membawa pembaca melihat bagaimana pembaratan terjadi dengan beragam reaksi, dari penuh selidik dengan tatapan nanar ke rasa bangga, dari keresahan sampai peniruan oleh kaum bumiputra.
Pembaratan tersebut terjadi dalam berbagai bidang. Dari busana, transportasi, alat fotografi, dan perabot rumah untuk menyebut beberapa contoh. Sederet benda yang bisa dikenakan oleh orang-orang bumiputra—meski baru bebas dinikmati segelintir kalangan.
Deddy Arsya pun menyinggung ide-ide dalam pendidikan-pengajaran, reformisme-Islam, daya uang, kapitalisme cetak, sampai emansipasi.
Melaju dan Menderu
Transportasi jelas diperlukan untuk mobilitas. Salah satu moda yang dibawa orang Eropa adalah kereta angin atau sepeda onthel. Pada awal abad XX, kendaraan ini sempat menjadi tren, termasuk di kota-kota kolonial macam Padang Panjang.
Semula, sepeda digunakan untuk membantu gerak kerja-kerja pegawai kolonial. Pamor sepeda melejit dan jadi primadona. Penggunaan—dan ketenaran—yang tinggi pun menumbuhkan bengkel-bengkel untuk reparasi dan perawatan.
Namun, kondisi itu tak berlangsung lama. Kehadiran kendaraan yang lebih modern apalagi bermesin segera menggantikannya. Mobil, atau “kodok yang minum bensin” lekas menggeser popularitas sepeda sebagai kendaraan elite pribumi di Hindia Belanda, yang kali pertama dikenalkan sekira tahun 1898.
Baca juga: Mendialogkan Sains dan Agama
Jumlah kendaraan lantas naik dari tahun ke tahun. Kehadiran transportasi tak pelak membentuk konsepsi manusia baru yang melipat jarak dan bersigegas dengan waktu. Volume kendaraan yang meninggi sangat mungkin menimbulkan kecelakaan. Di sana, Hatta, menjadi salah satu orang yang menaiki auto dan mengalami kecelakaan.
Di jalan-jalan kolonial, bukan cuma auto yang melaju, ada pula pedati, bendi, dan kuda beban yang tempo awal abad XX masih dipakai banyak orang. Kepemilikan auto pun masih belum seberapa. Tak sedikit pula yang menggangap mobil sebagai benda yang aneh plus ganjil.
Apabila ada mobil yang rusak di jalan dekat kampung, “toea moeda datanglah melihat.” Gambaran ini di satu sisi menunjukkan antusiasme orang-orang terhadap produk modern ini, tetapi di sisi lain juga memperlihatkan “keasingan”-nya dalam keseharian masyarakat. (hlm. 51) Orang-orang di tanah jajahan penasaran sekaligus heran.
Merayakan Pesawat Kodak
Pada awal 1900-an, peralatan fotografi masih rumit dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Kamera tetap benda mewah. Meski demikian, berpose di hadapan pesawat Kodak sudah dianggap sebagai hal modern dan penanda kemajuan.
Seperti yang dilakukan A. Rivai, dokter asal Minangkabau keluaran STOVIA, yang saat tamat sekolah dokter, seketika pergi ke juru potret. A. Rivai juga boleh dibilang sudah terbaratkan segala-galanya: pikirannya, sikap hidupnya, termasuk pilihannya beristri noni Belanda.
Fotografi pelan-pelan mewabah di tanah koloni. Jajaran redaksi surat kabar Pandji Poestaka sampai mengundang tukang kodak untuk mengirimkan karyanya, dan yang berhasil dimuat mendapat honorioem atau wang hadiah.
Antusiasme para juru potret atas perlombaan tersebut rupanya melebihi ekspekstasi dewan redaksi, “dari tempat-tempat jang ketjil, jang soenji, jang sekali-kali tidak orang sangkakan, teroes-meneroes kami terima kiriman potret.” Demikian berita Pandji Poestaka di satu edisi tahun 1927. Tepat setahun usai kaum komunis melancarkan pemberontakan sporadis yang ada di Hindia Belanda, utamanya di Jawa dan Sumatra.
Baca juga: Janturan: Ruang dan Pesan
Orang-orang di surat kabar malah merayakan fotografi saat kaum komunis di mana-mana ditangkapi, gembongnya digantung di muka umum, sekian kapal orang dikirim ke Digul untuk menjalani pembuangan.
“Inilah foto yang proporsional secara tata letak,” kata redaktur koran itu mengomentari foto tubuh-tubuh kaum pemberontak yang koyak-koyak oleh peluru serdadu, bertumpuk-tumpuk dengan latar sebuah lokomotif di stasiun… (hlm. 110)
Lewat penjelasan Deddy Arsya perihal kelakuan orang Bumiputra ini, kita bisa tahu bahwa ada ironi yang benar-benar terjadi. “Kilat” kodak memancar di kala kaum komunis, kelompok yang getol melawan dan menyemai ide-ide revolusioner demi mengusir ketidakadilan di tanah jajahan, pelan-pelan menuju mati.
Gemerlap modernitas itu seolah membuai kaum bumiputra dengan elok, bahkan menina-bobokannya. Ironi seperti di atas sangat mungkin terulang zaman sekarang, saat realitas tak jauh-jauh amat dari khayalan, yang luhur bersebelahan dengan yang banal.
Kursi Goyang
Modernitas melesak sampai ke rumah-rumah keluarga di Padang Panjang. Benda-benda teranggap modern hadir dalam bentuk perkakas maupun furnitur. Aneka perabotan mestilah mahal dan mewah. Sebab, pada dasarnya, kekosongan rumah bukan corak Barat. Kekosongan tersebut perlu diisi. Beberapa di antaranya meja, kursi, almari, piano dan yang cukup menarik adalah kursi goyang.
Saya jadi ingat penggalan novel Semua yang Diisap Langit (2021) karya Pinto Anugrah. Novel yang mengusung latar Minangkabau pada era kolonial. Bungo Rabiah, salah satu tokoh utamanya, terperanjat saat melihat kursi goyang di rumah mertuanya.
“Kursi apa ini?” tanya Bungo Rabiah kebingungan.
“Namanya kursi goyang… Rumah gadang mana selama ini yang mempunyai kursi, apa lagi kursi goyang? Tidak ada! Ini baru, kita memasuki zaman baru, Rangkayo! Lihatlah kursi goyang ini, ia bergoyang mengikuti perkembangan zaman.”
Penjelasan Tuan Tan Amo pada istrinya ini sangat representatif dalam mewakili semangat kaum bumiputra menapaki tangga modernitas, menyambut age of progress—meminjam istilah SC Burchell.
Sebelumnya, Deddy Arsya cukup dikenal sebagai sastrawan, menggubah puisi dan menulis prosa. Saat menyusun kompilasi tulisan dalam buku ini, Deddy Arsya tidak kehilangan gaya bahasa yang puitis dan luwes. Pembaca akan merasakannya saat melahap lembar demi lembar buku ini.
Judul: Merengkuh Djaman Kemajoean: Dinamika Modernitas Kota Kecil
Penulis: Dedy Arsya
Penerbit: Tanda Baca
Tahun Terbit: 2022
Jumlah halaman: xvi + 174
ISBN: 978-623-9397-76-0