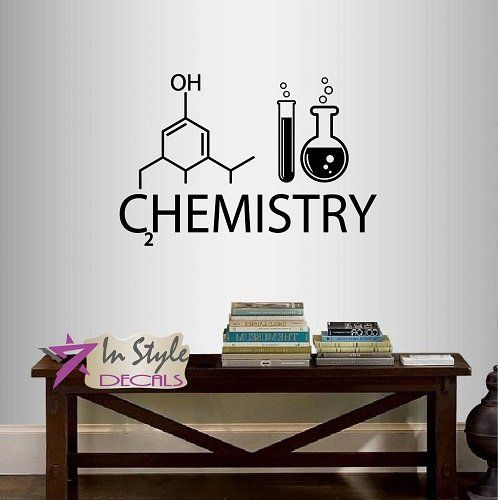
Kisah keluarga dan sains yang terhampar dalam novel Nenek Hebat dari Saga (2001) garapan Yosichi Shimada memberikan pelajaran penting bahwa keberadaan jejaring keluarga menjadi modal fundamental bagi seorang anak bertumbuh.
Tokoh anak, Akihiro Tokunaga menerima kenyataan pahit dengan terpaksa berpisah pada orangtuanya pasca dibomnya Jepang oleh pihak Sekutu. Kehidupan serba kurang dan sederhana adalah takdir yang harus diterima bersama neneknya.
Namun, siapa sangka, rajutan cerita dalam novel tersebut menyuguhkan pengalaman yang menegangkan, imajinasi yang fantastis, dan sikap yang penuh kreativitas. Dari uraian demi uraian yang ada, kita tahu kecerdasan seorang Nenek Osano dalam pengasuhan membingkai kemiskinan dengan metode pendidikan-pengasuhan yang penuh kejutan. Mengajari cucunya untuk menghayati keberadaan sains melalui tindakan keseharian.
Apa yang ada di cerita tersebut setidaknya menjadi penegasan, bahwa keluarga memiliki peran penting dalam memantik kebiasaan terhadap ilmu dan pengetahuan. Keluarga jadi wadah pertama guna diseminasi ide dan nalar sains. Berangkat dari kisah keluarga dan sains tersebut, agaknya, kita mulai kesulitan menemukan imajinasi pengasuhan anak dari keluarga di Indonesia pada abad XXI. Dalam pertumbuhan media digital, justru yang terjadi adalah peminggiran terhadap banyak isu terkait anak.
Ini tidak terlepas akan bagaimana media digital merasuk sampai mendominasi isu maupun kepentingan orang-orang dewasa. Akhirnya harus diakui, kelompok anak rentan mengalami atas apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Novia Utami (2023) dalam penelitiannya, misalnya, menjelaskan bagaimana perkembangan media digital, anak mudah dieksploitasi dengan dalih uang alias bisnis semata. Fenomena tersebut dinamai “Kidfluencer”.
Anak-anak tidak pernah dipandang sebagai subjek seutuhnya yang punya sifat aktif dan dinamis serta memiliki keinginan, pikiran, dan perasaannya sendiri. Tentu saja, anak merupa sosok yang memandang dirinya dari sudut pandangnya. Pemaksaan gagasan ala orang dewasa pada kanak membuat kanak tak mampu leluasa dalam mengekspresikan diri, sebab semua ada dalam koridor sekat dan aturan. Akibatnya, paradigma klasik yang mengatakan “anak-anak merupakan masa depan suatu bangsa” atau “bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak” menjadi terdengar klise.
Baca juga: Mendialogkan Sains dan Agama
Kenyataannya, anak-anak merupa sebuah industri baru yang menguntungkan lagi menggiurkan. Mereka dijajakan bak barang dagangan dalam berbagai kontes, media, dan iklan, sekaligus mereka juga dikondisikan untuk membeli barang dagangan tersebut (Dede Lilis CH. Subandy, 2009).
Yang menjadi masalah bukan terletak pada daya kreativitas yang dihasilkan anak, tetapi pada fungsi kontrol dan regulasi hukum mengenai umur yang belum memperbolehkan. Pada gagasan lebih luas, relasi antara anak-anak dengan media digital harus dipikirkan terkait dengan kesehatan mental, privasi, etika, moral, hingga potensi penyalahgunaan informasi baik data-data sensitive maupun privat.
Ruang Keluarga
Bertolak dari fenomena mutakhir ini, bagaimana posisi dan peran keluarga semestinya? Adaptasi maupun penyesuaian terhadap perubahan zaman adalah kelaziman dan tidak mungkin dimungkiri. Namun, jangan sampai terlena pada hal yang tidak kalah substansial.
Satu hal yang sejatinya menarik untuk digaungkan-diwacanakan dalam ruang keluarga mengenai dunia anak adalah integralisasi terhadap sains. Ini tak terlepas akan bagaimana kondisi yang ada, literasi sains di Indonesia secara umum masih rendah.
Fondasi mendasar dalam membentuk budaya dan kecakapan terhadap ilmu dan pengetahuan tentu adalah keluarga. Itu dilalui dengan segenap proses dan interaksi panjang antara orangtua dan anak. Di mana keberadaannya meliputi penyediaan bacaan, kemauan untuk memberikan cerita, hingga memberikan kebebasan anak dalam memacu imajinasi dan kreativitas.
Baca juga: (Keaksaraan) Majalah: Perempuan dan Anak
Orangtua dengan segenap ketersediaan bahan berperan penting di dalam memantik percakapan, memberi penjelasan, dan memancing keingintahuan dari anak mengenai berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar. Kemauan bercerita dan ajakan membaca dengan didasari pada pembiasaan menjadi resep manjur dalam mencukupi asupan ilmu.
Hal yang penting selanjutnya adalah di tengah dialog yang terjadi, perlu diinisiasi metode penyelidikan (inkuiri). Dengan artian, konsep itu sebagai penjelasan lebih lanjut dengan mencari landasan keilmuan atas apa yang dilihat-dialami. Umpamanya, melihat berbagai alat listrik yang difungsikannya setiap hari. Orangtua tidak lantas menyuruh menghindari alat tersebut dan melarangnya, tetapi membuka dialog untuk menyelidiki dan menalar.
Faktor Penghambat
Dalam kesenjangan yang senantiasa menjadi bayang-bayang kehidupan, satu faktor yang memang dihadapi keluarga di kalangan menengah ke bawah dalam proses integralisasi itu adalah kecukupan dalam pemenuhan instrumen. Baik itu penyediaan bahan bacaan secara berkala, peralatan sebagai pendekatan terhadap keilmuan, hingga ketersediaan waktu orangtua yang terbatas di tengah kesibukan dalam menjalani rutinitas kerja.
Kemiskinan menjadi satu faktor yang kerap menghambat proses keilmuan. Fakta ini lumrah dan telah terbukti dalam banyak riset. Salah satunya sempat dijelaskan dalam sebuah film dokumenter garapan Netflix, The Beginning of Life (2016). Di film, sebuah riset menjelaskan, perbedaan jumlah kosakata yang diterima anak usia 4 tahun di antara keluarga miskin dan berada merentang sekitar 30 juta.
Namun, kembali lagi, kita perlu belajar dalam kisah yang ada dalam novel Nenek Hebat dari Saga di atas. Kemiskinan bukanlah faktor penghambat. Kemiskinan belum tentu rintangan berat. Si nenek justru menaruh tindakan berarti atas keterbatasan dan kesulitan dalam keseharian dengan memanfaatkan momentum guna proses transformasi keilmuan.
Mungkin, Anda meyakini kisah keluarga dan sains itu hanya ada di cerita atau dongeng belaka. Namun, lihatlah, tidak sedikit dari para ilmuwan besar dan kondang, mendapati kemiskinan dalam perjalanan panjang yang dilakukan, sebelum meraih keberhasilan.







