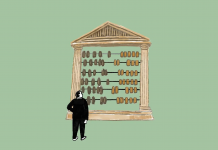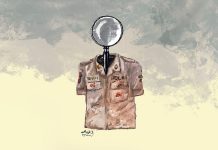Sejarah lahirnya hukum (fikih) senantiasa membutuhkan kaidah-kaidah secara rasionalitas sebagai pertimbangan penentu kebijakan tata negara. Semenjak Islam berkembang di Timur Tengah, persoalan hukum pasca kenabian telah berubah menjadi instrumen politik yang amat berbahaya.
Sebab, hukum pada umumnya tidak hanya sebagai aturan tertulis untuk kesejahteraan sosial, melainkan juga berlaku sebagai senjata oleh para pemangku kebijakan dan rezim penguasa yang otoriter nan hegemonik. Sejarah hukum pasca kenabian juga memunculkan beragam perbedaan tafsir yang acap kali menentukan polemik dalil dan dasar landasan teologis.
Situasi seperti ini tampaknya juga pernah terjadi dan berkembang di Indonesia. Pada tahun 1951, pernah terbit buku berjudul Alasan-Alasan Hukum Fakih (1951). Buku itu ditulis oleh R. Ng. Ihsanudin bin Alwi dan—setelah sampul dijuduli kitab Qowa’idul-Ahkam; Menerangkan Beberapa Qoi’dah Ilmu Usul Fiqh.
Baca juga: Relasi Islam di Panggung Sejarah
Buku ini, menurut saya cukup penting sebagai ingatan sejarah pelajaran hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Sebab kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pelajaran hukum kepada masyarakat, tetapi juga menjadi buku pedoman pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ihsanudin bin Alwi menulis karena rasa prihatin terhadap generasi muda, yang tidak tertarik menekuni kitab-kitab klasik berbahasa Arab guna memahami agama. Sehingga ia berinisiatif untuk menerangkan kaidah-kaidah dengan bahasa Indonesia untuk para pelajar dan masyarakat luas.
Ihsanudin bin Alwi memiliki latar belakang sebagai hakim, sekaligus ketua di Pengadilan Agama kota Madiun pada tahun 1951-an. Ia menulis buku tersebut dengan mengutip beberapa kitab babon seperti kitab Al-Isbach Wannadlair karangan Imam Djalaluddin ‘Abdur-Rachman bin Abubakar. Buku setebal 52 halaman ini pernah dicetak di Solo, pada tahun 1951.
Ihsanudin bin Alwi menulis karena rasa prihatin terhadap generasi muda, yang tidak tertarik menekuni kitab-kitab klasik berbahasa Arab guna memahami agama. Sehingga ia berinisiatif untuk menerangkan kaidah-kaidah dengan bahasa Indonesia untuk para pelajar dan masyarakat luas.
Kita bisa simak nasehatnya, “Kemudian harapan saja, kitab Risalah ini mudah-mudahan dapat mentjukupi sekedarnja bagi mereka jang berkewadjiban djuga mempeladjari ilmu usul fiqhi itu untuk memperluas dan memperdalam sebagian dari pengetahuan agama jang sungguh berguna bagi kepentingan didunia dan diachirat djua adanja”.
Ihsanudin bin Alwi menuliskan pelajaran kaidah-kaidah fikih sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat. Pada kenyataannya, perbedaan sudut pandang yang melahirkan berbagai kelompok keagamaan (Islam) semula berawal dari terbentuknya konsepsi hukum yang berbeda. Situasi ini mengakibatkan hukum dapat ditelaah secara tekstual, serta di lain sisi kontekstual.
Ihsanudin bin Alwi dalam buku ini lebih cenderung mencoba memberikan penengah, yaitu memadukan teks dasar hukum dan logika (rasional) untuk memahami situasi terkait. Sebab, jika kita membaca kaidah-kaidah hukum yang ditulis oleh Ihsanudin bin Alwi, ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan perubahan aturan hukum.
Misalnya, dalam kaidah: Dhorurat itu dapat memperkenakan perkara-perkara yang dilarang syara’. Seperti dalam situasi di mana kita sedang terdampar atau terjebak di hutan, kita bakal sulit menemukan makanan yang halal. Makanan yang kita peroleh umpamanya hanya daging babi, daging anjing, jamur yang membuyarkan kesadaran, atau minuman yang mengandung alkohol. Sehingga para Ulama memperbolehkan makanan tersebut dimakan asalkan secukupnya.
Sebab situasi-kondisi yang sulit seperti contoh di atas tentu dapat kita maklumi sebagai kaidah hukum. Bahwa memakan makanan haram jauh lebih baik ketimbang kita kehilangan nyawa ketika sedang dalam kesulitan. Maka, dalam konteks ini, Ihsanudin bin Alwi memunculkan hukum dan rasionalitas itu bisa saling berkesinambungan dan berirama dalam mewujudkan kemaslahatan, tanpa berseberangan. Kemaslahatan dari hasil telaah kaidah-kaidah hukum tidak hanya bergerak pada persoalan ibadah, tetapi juga berkaitan sosial-keagamaan.

Ihsanudin bin Alwi membagi tiga bab secara mendalam ketika membahas usul fikih serta kaidah hukum. Yang cukup menarik, Ihsanudin bin Alwi menyampaikan persoalan hukum jinayah yang justru saya sendiri kurang sependapat dengannya. Pada penjelasan kaidah hukum jinayah, Ihsanudin bin Alwi hanya menggunakan pendekatan normatif-historis—yang hanya melihat teks literal Al-Qur’an.
Di dalam hukum jinayah (pidana Islam) ada pembagian hukum sesuai berat-ringannya suatu pelanggaran hukum. Ketiga hukuman tersebut memang memiliki dasar kuat dari teks (Al-Qur’an) yang dijadikan landasan hukum. Namun seiring perkembangan zaman, model hukuman seperti qisas dan hukuman hudud, seperti seorang pencuri dipotong tangan, membunuh dibalas membunuh, serta zina dicambuk dan didera, merupakan rekam jejak historis yang semestinya kita pikirkan melalui pendekatan filsafat.
Baca juga: Memahami Tafsir Ekologi
Jasser Auda dalam buku Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah (2008), tidak bisa menerima model hukuman klasik yang tidak melihat situasi-kondisi zaman yang semakin modern. Sebagai pemikir Islam kontemporer, Jasser Auda memberikan kritik sekaligus jalan keluar untuk memahami pesan-pesan Al-Qur’an secara mendalam.
Auda mengemukakan bahwa seseorang berhak memperoleh kehidupan yang sejahtera. Sehingga ia mengembangkan konsep Maqasid Syariah yang sudah digagas oleh Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan lain-lain. Konsep ini menitikberatkan pada tujuan hukum Islam yang semestinya melestarikan agama, jiwa, keturunan, kehormatan, harta benda, dan akal budi seseorang.
Penekanan inilah yang kemudian dijadikan pedoman bahwa usul fikih harus dan perlu didalami kembali sumber-sumber hukumnya melalui pendekatan maslahah-mursalah, urf, dan lain-lain.
Sehingga nantinya dapat memunculkan produk hukum yang tidak terkesan kaku dan tekstual. Selain itu, supaya produk hukum tidak hanya dijadikan alat komoditas dalam menentukan komoditas bercap halal-haram. Hukum harus berdiri kukuh, tak takluk dan tunduk mengacu permintaan pasar atau kepentingan kelompok.
Lemahnya rasionalitas dari diri kita dalam mempelajari hukum Islam sering menyeret paradigma hukum ke arah bisnis berlabel agama. Klepon yang tidak bersalah saja dihakimi haram dan tidak islami. Apakah orang Indonesia tidak rasional? Entahlah!