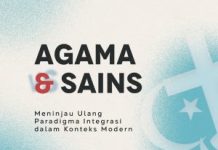Begitu pentingnya bahasa, menjadikan ahli saraf berkebangsaan Kanada, Donald B. Calne meletakkan satu bab khusus dalam Within Reason: Rationality and Human Behavior (1999). Di dalam buku yang pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh mendiang Parakitri T. Simbolon dengan judul Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia (Kepustakaan Populer Gramedia, 2004) tersebut, kita akan mendapatinya pada bagian ketiga, yakni berupa “Bahasa dan Nalar”.
Donald B. Clane dengan fasih menjelaskan keberadaan bahasa dalam tinjauan biologi molekuler dengan sesekali memberi konteks pada aspek sejarah dan susastra. Ia memberi penegasan akan keterhubungan nalar terhadap bahasa. Tulisnya dalam keterangan berupa: “Bahasa merupakan sistem lambang yang sangat tertata rapi guna menyampaikan informasi; lambang itu bisa disimpan, diingat, dan diolah dengan otak. Untuk menjaga kelenturan yang perlu bagi timbulnya bahasa yang kaya dan beragam, satuan kecil pada bahasa, bila dipisahkan, tidak boleh punya arti sendiri.”
Peletakan bahasa yang senantiasa berkoneksi pada kemauan bernalar itu naga-naganya terbetik dalam esai-esai sastrawan dan periset bahasa, Darmawati Majid, di buku terbarunya, Gratis Ongkir: Kelindan dan Sengkarut Bahasa (Gramedia Pustaka Utama, 2025). Ia melakukan pengamatan dan upaya interpretasi terhadap segenap perubahan yang terjadi di dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar, aktivitas tersebut menempatkan ruang virtual sebagai objek dominan dari aktivitas pengamatannya.
Ruang virtual sebagai bagian dunia digital yang ditopang beragam media sosial kiranya telah menjadi wilayah yang memperlihatkan pertarungan apa saja, tak terkecuali bahasa. Setakat dengan itu, interkoneksi yang sedemikian, membabar posisi bahasa di ruang digital sarat dengan perubahan makna. Perubahan itu rupanya tak bersifat natural, namun acap berkelindan dari sejumput motif; militer, ekonomi, budaya, politik, bahkan ideologi.
Dalam posisi tersebut, mafhum Darmawati kerap mengajak para pembaca untuk menilik beragam jenis kamus—alih-alih untuk meyakinkan kamus itu penting. Sebagai kasus, misalnya pada esai berjudul “Janda” dengan mengambil amatan pada viralnya sebuah video pemengaruh berasal dari Lampung yang membuat ramai kata “janda”. Pada waktu itu, kata tersebut ditujukan kepada salah seorang politisi senior di Indonesia. Dengan ramainya dari warganet, sontak kata itu pun ramai dibahas dan mendapati interpretasi berupa makna yang merendahkan.
Baca juga: Panggilan Buku dan Daya Magis Membaca
Darmawati menyigi bahwa makna kata “janda” yang membuat stereotip terhadap wanita dan mengandung konotasi itu telah berlangsung lama. Sebagai wacana alternatif, ia mendedah kajian manuskrip yang ada di sejarah kerajaan Bone—tepatnya adalah pernah ada sosok bernama We Cenra Datu Cinnong—yang menyandang satus janda, digambarkan sebagai: “Sosok berani dalam literatur-literatur mengenai perjuangan rakyat di bawah pemerintahan Raja La Pawawoi Karaeng Segeri saat melawan Belanda di Bone” (hlm. 1).
Darmawati adalah penulis yang lahir dan lama menetap di pesisir Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Itulah yang menjadikannya memiliki kekhasan dalam kepenulisan. Ya, di beberapa tulisan, selain mengingat kampung halaman, ia pamrih menggunakan literatur-literatur yang bersumber di Sulawesi dan mengisahkannya kepada pembaca. Bersamaan dengan itu, terjadilah dialog dalam teks yang dimunculkan.
Cara tersebut tentu saja memperkaya khazanah kebahasaan dan menjadi budaya tanding saat kuasa bahasa acap dimonopoli oleh pusat ibu kota. Seperti kasus di atas, ia kemudian berucap: “Kisah janda pemberani dalam manuskrip kuno pun tidak lagi berpengaruh sebab tenggelam dalam pencarian jejak digital” (hlm. 3).
Sementara itu, esai yang digunakan untuk judul buku, “Gratis Ongkir” kiranya menjadi salah satu esai yang menarik perhatian. Secara semantik, kata “gratis” telah berubah makna dalam frasa tersebut—yang boleh dikatakan mengingkari makna yang telah ditetapkan oleh kamus-kamus. “Jika dikaji lebih jauh, ada ketidakjujuran tersembunyi di balik frasa itu. Pada kenyataannya, kata gratis di sana tidak selalu diartikan sebagai ‘tidak dipungut pembayaran’ sebagaimana makna kata itu dalam kamus bahasa Indonesia” (hlm. 10-11).
Betapa pun, peristiwa yang melibatkan gratis ongkir itu menautkan bahasa dan praktik ekonomi. Kiranya penting untuk sejenak menengok buku garapan Douglas Atkin (2004), yang dalam bahasa Indonesia pernah diterjemahkan oleh Lina Susanti berjudul Membangun Kesetiaan Merek: Bagaimana Pemasaran Berbasis Komunitas Melejitkan Keuntungan dan Menguatkan Merek (Penerbit B-first, 2006). Bahasa, bagi Douglas Atkin menjadi bagian simbolisme, yang membuat makna menjadi mungkin. Terlepas manipulasi makna yang terjadi pada praktiknya, tentu upaya itu dalam pemasaran merujuk godaan terhadap para konsumen untuk berbelanja.
Pada hamparan besar, selain gratis ongkir, sekian tulisan dalam buku ini, menarik kita melihat bagaimana aktor politik akrobat mencipta makna, meski kerap keliru—alih-alih untuk mengatakan terjadinya perusakan bahasa. Beberapa tulisan itu antara lain adalah “Anggota”, “Tersandung”, “Main Dua Kaki”, “Tegak Lurus”, dan “Miskin”. Bahkan dalam esai “Anggota”, Darmawati membabarkan makna kata tersebut dalam konteks militer. Itu terjadi tiada lain hasil pengamatannya dalam sebuah dialog yang terjadi di salah satu episode dalam film serial Gadis Kretek (2023).
Baca juga: Menangkal Radikalisme Online Melalui Ilmu Kalam
Kata “anggota” memang identik pada lembaga kepolisian dan kemiliteran, yang tanpa menyebut polisi atau tentara, kata itu sudah mewakili dan kemudian diinterpretasikan perasaan aman dan aman. Namun, dalam konteks perkembangan bahasa dan situasi mutakhir, membuat kita untuk merasa penting merefleksikannya. Sebagaimana ungkap Darmawati: “Lalu, jika dewasa ini kita melihat bagaimana alat negara justru diturunkan untuk melawan dan mengusir warga dari tempat tinggalnya, menakut-nakuti masyarakat agar melepas haknya, bahkan untuk mengendalikan pilihan politik rakyat, kita jadi berpikir rasa-rasanya ada yang keliru. Kata anggota semakin jauh dari sesuatu yang tertib dan seharusnya memberi rasa aman” (hlm. 6).
Gejala itu tentu berhubungan dengan logika bahasa dalam politik, yang acap dimonopoli lalu ditafsir secara tunggal. Tentu saja, ini menjadi berbahaya dalam konteks keberadaan bahasa Indonesia, sebagaimana tersirat dari analisis di dalam buku.
Selain itu, yang mengemuka untuk meanjadikan kita terus mau mengurus bahasa Indonesia adalah dunia digital yang membuka ekses kemunculan bahasa asing. Darmawati menekankan pentingnya penyerapan. “Bahasa yang tak memiliki konsep yang kaya dan tidak pula diupayakan pemerkayaan kosakatanya lambat laun akan ditinggalkan penuturnya” (hlm. 19). Arkian, cara merawat bahasa memang benar harus dibarengi kemauan bernalar dan berpikir.
Judul : Gratis Ongkir: Kelindan dan Sengkarut Bahasa
Penulis : Darmawati Majid
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Ukuran : 14 cm x 21 cm; xiv + 122 Halaman
Cetakan: Pertama, April, 2025
ISBN : 978-602-06-8085-9
ISBN Digital : 978-602-06-8086-6