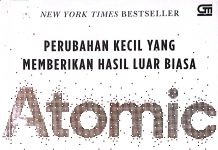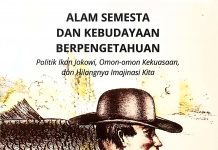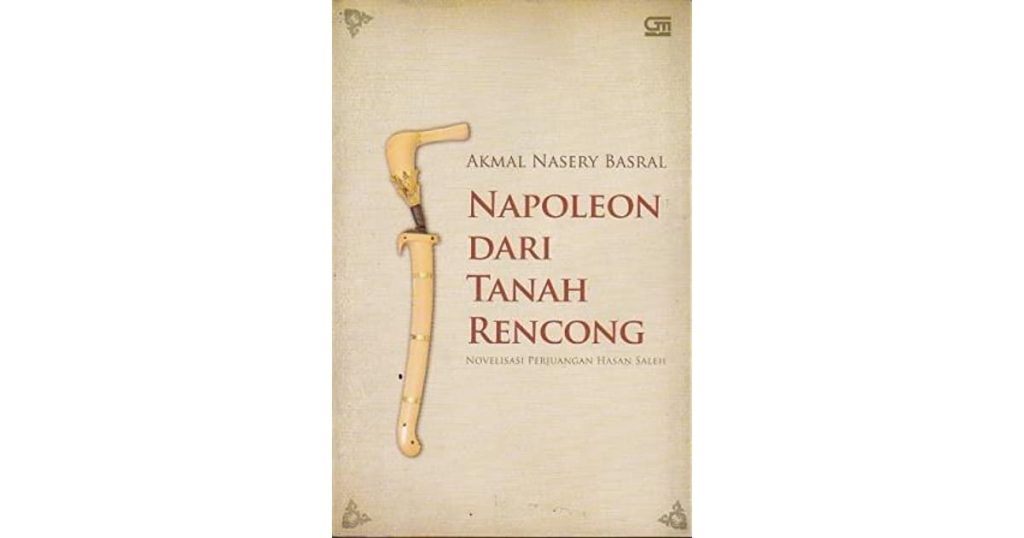
Sejarah memang tidak selalu indah, tetapi bukan berarti tidak pantas untuk dikenang dan diceritakan pada generasi penerus. Jika kalian menganggap cerita sejarah sering kelewat membosankan dan kurang kontekstual, saya merekomendasikan membaca buku ini. Gaya tutur dalam novel yang diangkat dari kisah heroisme ini mampu menggaet dentuman emosional pembaca lewat perjuangan Hasan Saleh.
Buku Napoleon dari Tanah Rencong (2013) karya Akmal Nasery Basral berisi perjuangan Hasan Saleh memberantas penjajah hingga lahir Daerah Istimewa Aceh. Pemilihan biografi yang dinovelisasi oleh Akmal tak lain adalah untuk menjangkau pembaca lebih luas. Meskipun banyak nama tokoh yang muncul bahkan hampir sama, tapi alur kisah terfokus pada Hasan Saleh. Buku ini juga mampu mengeksplorasi situasi dan mengaduk emosi pembaca.
Hasan Saleh merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Ismail Syekh, Ibrahim Saleh, Hasan Saleh, dan Yacob Aly. Keempat bersaudara tersebut berasal dari bapak yang berbeda. Meski begitu, mereka menjalin komunikasi yang hangat antar keluarga. Sosok laki-laki ini sendiri memiliki watak yang paling unik di antara saudara-saudaranya. Karakter kuat yang melekat seperti kecerdasan, kejujuran dan keberaniannya dapat menjadi teladan bagi generasi saat ini.
Hasan Saleh menghabiskan masa anak-anak untuk menempuh pendidikan Islam. Dia sempat berganti-ganti madrasah karena situasi Aceh yang tidak baik-baik saja. Tahun 1920, Belanda masih menguasai Aceh sehingga kondisi sosial masyarakat Aceh terbagi dua kubu, yaitu Teuku/Uleebalang (mata-mata belanda/pro-Belanda) dan Teungku (kalangan Ulama). Tentu saja Hasan Saleh termasuk golongan Teungku.
Pada 1943, saat Hasan Saleh memasuki usia remaja, dia meminta izin mengikuti sekolah militer bernama Kambu Yoin. Dia lolos seleksi dan akhirnya menempuh pendidikan militer Jepang hingga menjadi perwira. Pada 1939 terbentuklah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin Abu Daud Beureueh. Lewat perjuangan anggota PUSA dan tentara Jepang inilah, Aceh berhasil dikuasai oleh rakyat pribumi.
Narasi Perang Heroik
Novel susunan Akmal Nasery Basral ini benar-benar berisi sejarah masa lampau. Ia menyuguhkan alur tragis beriring sikap nasionalis yang mampu meletupkan imajinasi pembaca secara visual. Sebagai gambaran, adegan Kapten Hasan Saleh dalam memimpin perang di medan area. Akibat serangan NICA yang terus membombardir, kompi-kompi yang dibawahi Hasan Saleh kalang kabut karena minim persenjataan.
Hasan Saleh memutuskan menghancurkan jembatan Strabat dan tambang minyak pangkalan Berandan sebelum jatuh ke tangan Belanda. Dia mengeksekusi misi ini sendiri menaiki brompit, musabab akan sulit jika menggunakan mobil tank karena pesawat militer Belanda terus berpatroli. Kejadian naas menimpa Hasan Saleh, strategi yang digunakan meleset, dia dihujani peluru saat diperjalanan dan diserbu tembakan beruntun di jembatan Strabat.
Kejadian serupa menimpa Hasan Saleh saat ditugaskan memberantas kelompok Kahar Muzakar di Sulawesi. Batalyonnya dijanjikan mendapat tambahan senjata oleh pemerintah pusat, tapi janji itu tak kunjung ditepati. Penumpasan Kahar Muzakar akhirnya berakhir damai berkat negosiasi handal dari Muhammad Amir (utusan Kahar Muzakkar) dan Panglima Kaliwarang. Peran Hasan Saleh di sini sebagai mediator antara utusan Kahar Muzakar dengan Kaliwarang (Panglima Republik).
Baca juga: Pelangi di Bawah Satu Langit: Sistem Millet Utsmani sebagai Model Dakwah Kemanusiaan
Selanjutnya yang tak kalah dramatis adalah saat pejuang kemerdekaan dari tanah Sumatra ini ditugaskan menumpas pasukan Republik Maluku Selatan (RMS) di pulau Setan. Waktu itu, tak jauh berbeda dengan janji penambahan senjata. Alih-alih diberikan, senjata itu hanya kalimat semangat. Di situasi yang sudah kritis, Hasan Saleh sempat frustasi dan mengarahkan pistolnya di kepala bermaksud bunuh diri karena sudah tak ada yang peduli terhadap aduannya.
Akmal menyajikan narasi yang kokoh terhadap objektivitas karakter. Klimaks perang yang diceritakan dapat membakar emosi siapapun yang membaca. Saya kira, sejak diproklamirkan kemerdekaan, bangsa Indonesia benar-benar merdeka. Faktanya malah terjadi pertumpahan darah di beberapa daerah. Bahkan pembangkangan dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Saya teringat kata-kata Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”.
Beda Visi Misi dengan Pemerintah
Anggaplah politik sebagai telapak tangan, jika sejalan ia akan menengadah, menerima, menggenggam, jika berlawanan, ia akan menampik, tak mengenal bahkan memukul. Politik mengandung keinginan, ambisi, dan misteri. Seperti halnya peleburan Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurut analisis Hasan Saleh, hal tersebut akan membuat anggota Masyumi di Sumatera Utara melonjak naik, sehingga dapat memperkuat posisi Masyumi sebagai partai yang tidak hanya diterima di daerah Islam, melainkan juga daerah non-muslim.
Provinsi Aceh ingin memiliki daerah otonom sendiri, daerah yang dapat menegakkan syariat Islam. Visi tersebut pernah disampaikan oleh Abu Daud Beureueh saat Bung Karno mengunjungi Aceh pada 5 Juni 1947. Namun, hal ini tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Kekecewaan rakyat Aceh menguat ketika Bung Karno lebih condong kepada komunis, padahal sangat jelas kubu komunis menusuk dari belakang ketika republik kesulitan.
Setelah kemelut politik terus membuncah, keadaan Aceh semakin rumit sebab adanya perubahan besar dalam peta kekuatan militer. Razia Sukiman dilakukan untuk menyita senjata gelap yang disimpan pendukung komunis. Tetapi di Negeri Aceh sebaliknya, aparat lebih banyak menciduk anggota PUSA yang justru merupakan penentang utama pihak komunis. Hal inilah yang mendasari alasan pokok Hasan Saleh memilih angkat senjata melawan pemerintah pusat dan menggabungkan diri dengan Darul Islam atau lazim tersebut DI/TII.
Pecah Kongsi
Setelah bergabungnya PUSA dengan DI/TII yang dipimpin Abu Daud Beureueh ternyata sering terjadi perbedaan pendapat dengan Hasan Saleh. Pertama, mengenai strategi perang yang akan digunakan. Kedua, mengenai hak demokrasi pada pemilu 1955. Dan, ketiga, keputusan yang diambil tentang konsepsi Prinsipil dan Bijaksana yang ditawarkan pemerintah.
Sepanjang 1956 sesungguhnya bukan hanya Aceh yang semakin membara. Di beberapa daerah seperti Palembang, Makassar dan Padang muncul perlawanan lokal. Pertarungan politik di Pusat (baca: Jakarta) juga tak kalah panas setelah Wakil Presiden Muh. Hatta memilih mengundurkan diri ketimbang terus bekerja sama dengan Soekarno. Sementara Aceh semakin membara setelah peristiwa rapat Cubo, perbedaan arugemtasi dengan Wali Negara (Abu Daud Beureueh) semakin runcing.
Baca juga: Merajut Kembali Makna Istimewa
Bulan Desember 1958, Hasan Saleh didatangi oleh KSAD Jenderal Nasution dari Kutaraja yang menawarkan konsep perdamaian. Ia menyampaikan visi kepada Wali Negara, namun Wali Negara bersikeras ingin tetap melakukan perang. Akhirnya Majelis Syura pecah pendapat hingga Maret 1959 Hasan Saleh mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Wali Negara (Abu Daud beureueh) kepada Dewan Revolusi.
Setelah kekuasaan dialihkan, Dewan Revolusi menggelar sidang yang isinya menuntut diberikannya status “Daerah Istimewa” kepada Aceh seperti Yogyakarta. Dua bulan kemudian, pada Mei 1959 rombongan Pemerintah Pusat datang ke Kutaraja yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi untuk membawa bingkisan kesepakatan. Perdebatan sengit dilakukan Hasan Saleh agar tuntutannya dikabulkan. Akhirnya setelah negosiasi panjang, pada 26 Mei 1959 Aceh diberikan status Daerah Istimewa melalui SK No. 1/Missi/1959.
Penulisan novel tanah rencong lahir bukan semata tercipta melalui imajinasi Akmal saja, ia melakukan riset ke beberapa tempat seperti Pulau Kameng (dusun kelahiran Hasan Saleh), Sumatera Utara (tempat pecahnya perang Medan Area) hingga ke Sidikalang (tempat desersi pemberontakan). Akmal juga mewawancarai sejumlah narasumber untuk mengetahui kejadian yang relevan sehingga membikin ruh cerita makin hidup.[]