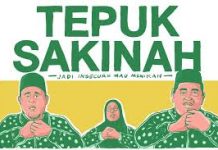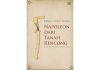Masyarakat Tegalsambi merayakan tradisi dengan api. Elemen ini menjadi aspek penting dalam perayaan tahunan yang terkenal luas disebut Perang obor. Sebuah tradisi ini sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda yang memiliki sejarah panjang.
Tradisi perang obor dilakukan pada bulan Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Tradisi ini berhubungan erat dengan peristiwa yang memiliki arti penting. Ritual perang obor di Jepara ini mencandrakan gambaran perihal kepercayaan masyarakat lokal untuk selalu merayakan ritual saban tahun secara rutin. Hal ini merupa wujud daripada masyarakat sekitar yang masih nguri-nguri ritual tersebut (Efa 2019:256).
Perang obor merupa sebuah ritual leluhur yang diyakini sebagai upaya resistensi dari bencana. Tradisi ini menampilkan aksi memukulkan blarak (pelepah kelapa) dan klaras (daun pisang kering) yang diikat jadi satu dengan tali bambu, lalu dibakar menjadi senjata pokok dalam perang obor.
Ratusan senjata itu kemudian digunakan untuk saling serang bak di medan perang. Api yang berkobar dimana-mana memanas dan menyala merah seolah-olah tempat tersebut merupakan tempat pertaruhan: kalah atau menang. Meski dalam prosesi perang obor cukup berbahaya, tradisi ini tetap dilestarikan dan mampu eksistensi, bahkan sampai menjadi menyita perhatian dari masyarakat luar Jepara.
Antusias ini tak terlepas dari rajutan sejarah masa silam dari pertingkaian dua leluhur desa Tegalsambi.
Riwayat Pertikaian
Tradisi perang obor muncul berawal dari kisah dua leluhur desa di Tegalsambi: Kiai Babadan dan Mbah Gemblong. Pada masa yang lalu, tinggal seorang pria kaya bernama Mbah Babadan yang memiliki banyak hewan ternak, dari kerbau sampai sapi. Ia sampai kewalahan mengurus semua hewan ternaknya seorang diri, hingga akhirnya tak sanggup.
Oleh karna itu, Kiai Babadan meminta bantuan Mbah Gemblong untuk ikut mengurus ternak-ternaknya. Mbah Gemblong dikenal sebagai sosok yang rajin dan telaten dalam merawat hewan ternak dengan baik.
Suatu ketika, kala Mbah Gemblong sedang mengembala hewan ternak di tepian sungai, ia melihat banyak ikan di sana. Terbersit di benak Mbah Gemblong untuk menangkap ikan lalu membakar hasil tangkapannya di dalam kandang ternak. Hal tersebut dilakukan Mbah Gemblong bukan hanya sekali.
Baca juga: Ponpes Hanacaraka: Membumikan Walisongo lewat Lirik Lagu
Namun, terjadi salah persepsi antar keduannya lantaran dari waktu ke waktu banyak hewan ternak Kiai Babadan mulai kurus hingga jatuh sakit. Kiai Babadan mulai curiga dengan hal yang dialami ternaknya.
Di kemudian hari, Mbah Gemblong sedang asyik memancing dan selanjutnya memasak ikan-ikan. Setelahnya, Kiai Babadan melihat Mbah Gemblong sedang asyik makan ikan. Terang saja, Kiai Babadan mengira Mbah Gemblong tak menunaikan tugas mengurus ternak sebagaimana mestinya. Seketika itu pula Kiai Babadan marah kemudian mengambil obor pelepah kelapa yang dibakar ada lalu memukulkannya diam-diam ke Mbah Gemblong. Sebab merasa tak terima dipermalukan demikian, Mbah Gemblong ikut mengambil blarak dan berusaha membalasnya.
Akibatnya, berlangsungnya perang obor di sekitar kandang yang membuat kandang ternak terbakar dan kobaran api yang begitu besar membuat semua hewan ternak yang mulanya sakit lari tunggang-langgang. Terkejut melihat ada sesuatu yang aneh, seluruh hewan ternak terlihat kembali sehat dan akhirnya mereka pun mengakhiri saling serang dengan. Peristiwa inilah yang mendasari munculnya keyakinan bahwa perang obor merupakan suatu ikhtiar menolak bala.
Serangkaian dari Sedekah Bumi
Sebagai representasi dari tradisi, anak-cucu Kiai Babadan dan Mbah Gemblong melaksanakan upacara perang obor di Jepara hingga kini. Pelaksanaan tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian hajat sedekah bumi. Upacara ini bertujuan untuk melangitkan rasa syukur atas hasil panen dari warga desa yang sangat berbeda dari daerah lain.
Sebelum itu, terdapat serentetan agenda sebelum upacara perang obor. Sekitar satu bulan sebelum hari H berlangsung acara barikan di makam sesepuh dan leluhur desa Tegalsambi. Adapun makam yang diziarahi yaitu Mbah Tegal, Mbah Gemblong, Syaikh Rofi’i, Mbah Sudimoro, Mbah Surgi Manis, Mbah Tunggul Wulung, Kiai Babatan, Mbah Sorogaten, Mbah Datuk Sulaiman dan Mbah Towikromo. Prosesi ini dilengkapi adanya ancak atau tempat untuk menaruh sesaji yang nantinya akan ditempatkan di berbagai titik yang beda. Sesaji tersebut adalah sebentuk penghormatan kepada leluhur.
Ada pula khataman Al-Qur’an bil ghoib yang dilakukan di masjid Baitul Dzakirin desa Tegalsambi. Khataman ini tidak lain merupakan ungkapan rasa Syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas hasil panen dan kekayaan yang berlimpah yang telah diberikan.
Baca juga: Tradisi Munggahan di Tatar Sunda
Selain itu, upacara dilengkapi dengan pagelaran wayang kulit. Ada prosesi untuk kirab pusaka pusaka bernama Pedang Gendir Gambang Sari dan Podang Sari, sebuah arca di masjid dan sebuah beduk yang dipercayai warisan Sunan Kalijaga. Benda pusaka ini dianggap mempunyai kekuatan ghaib yang memproteksi segenap warga desa dari segala musibah.
Panjatan doa kepada yang maha kuasa dipimpin oleh kepala desa. Seusai berdoa, kepala desa menyiapkan kembang setaman untuk ritual mengganti sarung pusaka yang melekat pada benda tersebut. Setelah dicuci dengan air bunga aneka rupa dan warna, kemudian dimasukan ke sarung baru. Air bekas sesi pencucian tak dibuang begitu saja, melainkan menjadi obat khusus yang terbuat dari minyak kelapa asli, yang berkhasiat menyembuhkan para peserta perang obor di Jepara yang menderita luka bakar (Zainal 2011: 90).
Dari serangkaian acara dari sedekah bumi yang menyertakan perang obor di dalamnya, dapat disimpulkan bahwa ada akulturasi dan presepsi kosmologis dalam budaya Jawa serta simbol-simbol yang memperkuat motivasi dan mendasari falsafah kehidupan. Fundamen di sekitar kita inilah yang, sudah semestinya, kita rawat sama-sama.