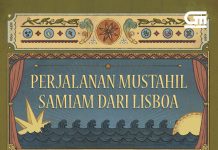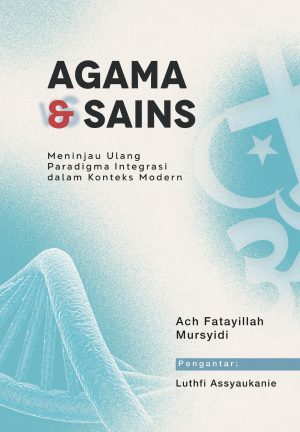
Di dua dekade lalu, mendiang Nirwan Ahmad Arsuka menyajikan esai berjudul “Imajinasi Ilahi” dalam Majalah Azzikra edisi Juni 2005. Pada esai tersebut, budayawan dan komunikator sains itu mendedah kisah lama pertengkaran sains dan agama yang merujuk pada “kambing hitam” para aktor intelektual di masanya. Baruch Spinoza dalam sejarah Yahudi, Galileo Galilei dan Giordano Bruno dalam sejarah Kristen, serta Abdus Salam dalam sejarah Islam. Mereka menjadi korban atas keangkuhan cara pandang agama terhadap nalar ilmiah.
Nirwan kemudian mengajukan argumen menarik. Ucapnya begini: “Penyebab tunggal semua ini adalah tiadanya metode, yang tangguh dan teruji, dalam mengadapi imajinasi, dalam menapis sekaligus memaksimalkan keliaran imajinasi manusia. Agama-agama belum punya, lebih tepatnya: belum mengembangkan, sejenis ‘metode religius’ yang setara dengan ‘metode ilmiah’ pengetahuan modern.”
Gugatan Nirwan kiranya penting untuk mendedah tawaran gagasan dalam buku garapan Ach Fatayillah Mursyidi yang kemudian saya sebut AFM. Secara penentuan judul, ia masih samar menentukan gagasan akan relasi yang ditawarkannya. Sebab, meski telah memunculkan kata “dan”, dalam sampul buku terbayangi istilah “vs”. Kiranya hal tersebut mengartikan bahwa betapa pun dengan sejarah panjang yang ada, sains beserta agama tidaklah mudah ditafsirkan secara tunggal.
AFM berangkat dari gagasan intelektual kelahiran Beijing, Tiongkok, 5 Oktober 1923 dan pernah menjadi guru besar bidang fisika dan teologi di Carleton College, Amerika Serikat, Ian G. Barbour, berupa kategori hubungan sains dengan agama lewat beberapa karyanya. Terhadap tawaran itu, AFM melakukan rekonstruksi dan melontarkan kritik, sembari kemudian mencari alternatif atas pergulatan intelektual yang dilaluinya. Dalam konteks Indonesia, terhadap Barbour, kita hutang rasa pada penerbit Mizan. Salah satu karya Barbour (2000), When Science Meets: Religion Enemies, Strangers, or Patners jauh hari hadir pada kalangan pembaca.
Baca juga: Catatan Historis dalam Balutan Mistis Dunia Semar Lembu
Buku tersebut pernah diterjemahkan oleh E. R. Muhammad dan diterbitkan Mizan pada 2002, dengan berjudulkan Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama. Di sana kita akan menemukan pembabaran tawaran yang diskemakan Barbour, yang masing-masing terdiri dari konflik, independen, dialog, dan integrasi. Perlu kita pahami, bahwa memang tiap kategori itu memiliki analisis yang kemudian mencuatkan kelebihan dan kekurangannya.
Hal itu pula yang kemudian ditelaah oleh AFM. Meski sepintas terlihat melakukan pendefinisan ulang, naga-naganya konstruksi yang melekat pada gagasan AFM cenderung dekat pada integrasi. “Sains dan agama bukan dua bidang disiplin yang lahir dari ruang yang hampa melalui aktivitas kognitif yang mandiri. Keduanya selalu melibatkan sejarah pergulatan manusia dengan lingkungannya secara kontinu dan kontekstual” (halaman 126).
Kesalinghubungan
Gagasan itu kemudian diperkuat oleh AFM dengan pertimbangan praktis dalam ranah sosiologi dan psikologi. Dengan cara pandang membawa kerangka agama dan sains pada fenomena yang terjadi, agaknya dipandang lebih berarti. Tiada lain dan tiada bukan adalah kesalinghubungan sains dan agama, yang dengan demikian memiliki peranan masing-masing. Pembabakan itu agaknya dapat kita tinjau dalam beberapa fenomena mutakhir.
Misalkan meruyaknya wabah pandemi Covid-19 yang di Indonesia berlangsung sejak 2020. Covid-19 adalah situasi yang menabalkan bahwa makhluk ukuran kecil (mikroskopik) yang dapat mematikan manusia. Keberadaannya mengharuskan kita sadar terhadap sains. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mencegah penyebarannya berupa menghindari kerumunan adalah pertimbangan yang logis dan ilmiah.
Ach Fatayillah Mursyidi kiranya penting untuk menjadikan titik berangkat refleksi guna mendorong kita untuk terus bernalar dan berpikir. Ada ruang di antara sains dan agama yang masih samar—kemudian mau memantik kita untuk menafsirkan secara terus-menerus menuju proses menjadi
Upaya itu juga menggeser paradigma beragama, dengan perlu menunda dan bahkan menghentikan tindakan spiritual di rumah ibadah secara berkerumun. Keberterimaan agama dalam posisi ini meski tak sedikit juga bersikap kontra pada mulanya—kiranya menjadi relasi sempurna antara sains dan agama. Alih-alih untuk menegaskan, bahwa keberadaan Tuhan semata-mata tidak di masjid, vihara, pura, klenteng, maupun gereja—namun terletak pada setiap umat beragama dengan kerendahan hati dan keterbukaan bahwa beragama itu perlu rasional.
Itu menguatkan gagasan Greg Soetomo berjudul “Sains dan Religusitas” di Majalah Basis edisi Desember tahun 1993. Ungkapnya: “Integrasi iman dan ilmu menjadi mungkin kalau di sana ada dialog yang terbuka di antara pelaku keduanya. Dialog hanya berlangsung secara sehat kalau keduanya memahami duduk perkaranya, titik tolak yang diambil, serta argumentasi-argumentasi yang dibangun dari masing-masing pihak baik dalam bidang sains-teknologi maupun iman secara filosofis maupun teologis.”
Konteks Kini
Apa yang perlu dikontekstualisaikan di masa kini? Sains dengan anak kandung bernama teknologi teruslah menggeliat dengan landasan metodologi ilmiah yang senantiasa diperbarui untuk menuju utuh, lengkap, dan sempurna. Bias konflik yang terjadi pada konteks keberadaan agama, sebagaimana diungkapkan pengasuh STF Al Farabi Malang, Ach Dhofir Zuhry (2023) dari proses sekulerisasi. Dhofir menjelaskan: “Sekulerisasi mengubah segala apa yang dahulu kita anggap sihir menjadi sains. Dan, sains adalah penantang utama bagi agama yang dimulai dianggap mitos.”
Agaknya itu seturut dengan gagasan pemikir Barat, utamanya mereka yang mengklaim ateis. Seperti misalkan di Amerika Serikat bercokol “Empat Penunggang Ateisme Baru”, yang memunculkan tokoh macam Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, dan Christopher Hitchens. Ateisme berangkat dengan acuan naturalisme metodologis, yang memang dalam ruang gagasan memunculkan perdebatan panjang. Itu pula yang menjadikan sosok Karen Armstrong turut andil dalam merespons gugatan pada teologi dari mereka para pemegang teguh ateisme.
“Literatur-literatur yang ditulis oleh empat pemuka ateisme baru dan para simpatisannya tersebut membuka kesadaran mereka tentang adanya kesenjangan epistemik yang sulit dijembatani antara agama dan sains….Hal ini diperkuat oleh sejumlah fakta bahwa agama (bisa juga dibaca oknum beragama) justru menjadi penyebab, alih-alih solusi, bagi isu-isu sosial dan politik di sekitar mereka” (halaman 218).
Baca juga: Pendidikan, Buku, dan Ilmuwan
Pernyataan AFM kiranya penting untuk menjadikan titik berangkat refleksi guna mendorong kita untuk terus bernalar dan berpikir. Ada ruang di antara sains dan agama yang masih samar—kemudian mau memantik kita untuk menafsirkan secara terus-menerus menuju proses menjadi. Meski demikian, pasti ada batas yang tak bisa atau bahkan tak perlu ditafsirkan. Alih-alih menegaskan bahwa dua aspek itu dalam peradaban manusia memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi.
Mungkin sebagaimana kutipan awal dari Nirwan Ahmad Arsuka tadi yang pernah mengangankan agama kemudian memiliki “metode religius”. Dengan arti bahwa agama yang mengutamakan keterbukaan untuk ikut serta menjadi bagian relevansi kompleksitas zaman. Itu agaknya perlu menjadikan koreksi atas kata pengantar dalam buku AFM yang ditulis cendekiawan Luthfi Assyaukanie, yang dengan tegas mengatakan tak perlu dialog antara agama dengan sains.
Ungkapan itu kiranya menyiratkan ketertutupan diri yang bisa jadi dampak dari jebakan wabah dikotomi pikiran—akhirnya hanya mengandaikan agama dan sains senantiasa berkonflik.[]
Identitas Buku
Judul : Agama dan Sains: Meninjau Ulang Paradigma Integrasi dalam Konteks Modern
Penulis : Ach Fatayillah Mursyidi
Penerbit : Cantrik Pustaka
Ukuran : 14 cm x 20 cm; 296 Halaman
Tahun Terbit : Cetakan Pertama, Mei, 2025
ISBN : 978-623-139-094-3