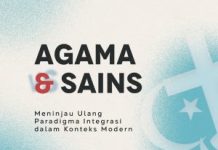Kajian ilmu Tasawuf atau Sufisme selalu menarik untuk dibahas. Sederet tokoh tasawuf bermunculan di berbagai kepustakaan dunia dengan mengusung nilai dan ajaran yang berbeda pula. Umpamanya, Al-Ghazali lewat karangan paling mashyurnya Ihya’ Ulumuddin, Ibnu Arabi, Hasan al-Basri, Rabiah al-Adawiyah, al-Hallaj, dan sebagainya.
Berbagai ajaran mereka meresap dan merasuk ke setiap sanubari sufi yang ada di tanah Nusantara, satu di antaranya ajaran Wahdah al-Wujud.
Wahdah al-Wujud menjadi ajaran yang cukup digemari oleh sufi-sufi Jawa dan para pujangga di daerah pedalaman Jawa Selatan. Simuh mengatakan ajaran ini diserap dan dikembangkan para pujangga kejawen periode Kartasura dan Surakarta lewat karya sastra jawa, yakni sastra suluk (hlm. 18).
Buku Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa bisa menjadi rujukan siapa saja yang ingin mendalami esensi tasawuf yang tumbuh di Jawa pada era Mataram Islam. Mula-mula, buku ini akan membawa kita bernostalgia dengan pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dalam Islam. Yang mana tasawuf sendiri terbagi menjadi dua golongan yakni tasawuf islam dan tasawuf murni (mistikisme).
Tasawuf Islam lebih condong dengan ajaran abid dan zahid dengan mengedepankan ketekunan dalam beribadah dan tidak tamak dengan kehidupan duniawi. Sedang tasawuf murni atau mistikisme cenderung terhadap pencarian hakikat Tuhan lewat jalur meditasi penghayatan kasyaf guna mencari fana’ dan memuncak pada makrifattullah.
Transendental Mistik dan Union Mistik
Ajaran tasawuf ini oleh Simuh dibedakan menjadi dua yaitu transendental mistik dan union mistik. Yakni paham mistik yang mempertahankan adanya perbedaan yang esensial antara manusia sebagai mahkluk dan Tuhan sebagai Sang Khaliq. Sebaliknya, union mistik memandang Tuhan sebagai zat yang imanen bersemayam dalam alam semesta dan dalam diri manusia (hlm. 45).
Paham transendental mistik dianut Al-Ghazali dan mayoritas sufi, sementara paham union mistik dianut oleh Ibnu Arabi, al-Hallaj, Hamzah Fansuri, Syamsudin Pasai, dan sebagainya.
Baca juga: Pendidikan di Kerajaan Langkat
Kemudian beranjak, Simuh mendedahkan mengenai konsepsi pokok-pokok pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf lewat rumusan distansi, konsentrasi, iluminasi atau kasyaf dan insan kamil. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju makrifat kepada Tuhan hanya bisa ditempuh dengan cara-cara tersebut. Lewat jalan penyucian hati agar membina suasana hati yang suci dan terbebas dari ikatan duniawi.
Ditambah dengan konsentrasi pada lantunan dzikir yang selalu dipanjatkan demi terwujudnya penghayatan kasyaf dengan mengalami fana’ dan tersikaplah tabir-tabir penutup agar dapat menuntun manusia menjadi manusia sempurna (insan kamil).
Al-Ghazali merupakan sufi besar yang berhasil mempertemukan ajaran ilmu syariat dengan ilmu hakikat (tasawuf). Namun, ia terlalu mengagung-agungkan tentang ajaran manusia sempurna (insan kamil). Alhasil, ajaran tasawuf sepeninggal beliau kembali menjadi tasawuf mistik.
Begitu juga dengan Nusantara, khususnya Jawa. Ajaran tasawuf martabat tujuh yang bermuara pada teori tajalliat-nya Ibnu Arabi menjadi ajaran yang paling di gemari para pujangga keraton yang kemudian diadaptasi dalam karya susastra Jawa yang berupa serat, suluk dan wirid.
Simuh dengan gamblang menjelaskan dari mana akar ajaran mistik ini berasal. Ajaran tasawuf mistik ini disinyalir akibat pengaruh empat sufi besar dari Aceh yang turut mengembangkan ajaran Wahdah al-Wujud itu. Sebutlah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Nuruddin ar-Raniri dan Abdul ar-Rauf Singkel.
Keempat sufi besar tersebut merupakan penganut tawasuf mistik atau dalam bahasa buku ini disebut dengan union mistik. Nampaknya mereka terpesona pada konsep martabat tujuh pengembangan konsep tajalliat-nya Ibnu Arabi
Sampai pada akhirnya, Abdul Rauf punya seorang murid yang berasal dari Jawa Barat bernama Abdul Muhyi—atau yang sering dijuluki sebagai “waliyullah negeri Priyangan”. Atas jasa Abdul Muhyi inilah ajaran tasawuf mistik atau yang kelak menjadi ajaran tarekat syaththariyah, menyebar di Jawa dan mempengaruhi corak sastra Jawa.
Kemudian lahir banyak karya Jawa berupa sastra serat, suluk, dan wirid yang bernapaskan ajaran martabat tujuh. Contohnya seperti Serat Centhini, Serat Cebolek, Wirid Hidayat Jati, Suluk Suksma Lelana, Serat Wulang reh, Serat Wedhatama, Serat Sabda Jati, Serat Pamoring Kawula Gusti, Serat Saloka Jiwa, dsb.
Semua karya sastra produk pujangga keraton tersebut berisi tentang ajaran Wahdah al-Wujud sebagaimana yang diajarkan Ibnu Arabi. Ajaran tasawuf mistik banyak terserap dalam karya sastra di Jawa, sebab para pujangga saat itu memang penganut tarekat syaththariyah, jadi hal ini lumrah adanya. Karya-karya itulah yang menjadi tolok ukur ajaran tasawuf mistik santer di tanah Jawa
Membahasakan Kejawen
Hal yang menarik dan selalu menjadi pembahasan dalam buku ini adalah term kejawen yang sebagai mana disebut Simuh sebagai ajaran Islam Jawa (islam kejawaan). Simuh menanggap ajaran mistik, kebatinan dan penghayat kepercayaan merupakan hal yang sejenis dengan ajaran paham theosophy.
Pandangan Simuh ini rupanya disanggah habis-habisan Irfan Afifi dalam buku Saya, Jawa dan Islam (2019). Irfan Afifi menganggap terminologi Kejawen atau yang diklaim sebagai aliran kebatinan ini baru muncul pada tahun 1930-an hinga 1960-an sebagai corak keagamaan baru dalam gerakan theosofi.
Baca juga: Mengingat Kembali Bahasa Simbol
Jadi, niscaya kurang tepat apabila term kejawen digunakan sebagai interpretasi Islam di Jawa sebab term tersebut baru muncul pada tahun 1930-an. Penyebutan kejawen merupakan nada peyoratif dari makna aslinya yakni Islam Jawa.
Penyebutan kejawen merupakan nada peyoratif dari makna aslinya yakni Islam Jawa.
Begitu pun dengan Mark Woodward. Penggunaan term kejawen dirasa kurang tepat sebab menurutnya dalam buku Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan (1999), “Agama Masyarakat Jawa adalah Islam, sebab aspek-aspek doktrin Islam (esoterime Islam) telah mengganti Hindhuisme dan Budhisme sebagai aksioma kebudayaan”.
Sekali lagi, Irfan dan Woodward mufakat bahwa identitas masyarakat Jawa beserta perangkat kebudayaannya merupakan Islam, tak ada penghayat kebatinan, kejawen, theosofi, dsb.
Hal lain yang mengundang perhatian dalam buku ini yakni kondisi kehidupan sosial-politik istana selepas Perang Jawa—yang dikata relatif agak tenang. Sebab, kekuasaan social-politik keraton telah ditelanjangi oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, simbol raja tanah Jawa masih dipertahankan oleh kolonial.
Hal ini lantas disangkal lagi oleh Irfan Afifi dalam esai Islam Nusantara: Kritik Diri (2021). Ia menuturkan pasca kekalahan Perang Jawa (1825-1830) timbul kegelisahan dan traumatik kolektif dari kolonial perihal kekuatan Islam.
Kemudian muncul ide untuk menegasikan Islam dari kultur kehidupan masyarakat Jawa. Usaha ini dibalut dengan politik kebudayaan pecah belah dengan di bentuknya Het Instituut voor de javanesche Taal (baca: Institut Javanologi). Mereka mencoba mendegradasi Islam dan melabeli Islam sebagai agama sinkretik dan jauh dari nilai Jawa Esensial.
Kondisi social, politik, dan ekonomi di Jawa waktu itu bisa dikatakan hancur berantakan. Selepas pemberontakan Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya berhasil ditumpas, pihak Kolonial lekas menerapkan sistem tanam paksa atau culture stelsel (1830).
Dengan sistem yang amat berat ini, masyarakat Jawa ditindas habis-habisan yang dengan ini menyangkal hipotesis awal tentang kondisi sosial-politik yang relatif tenang di Jawa.
Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2017) pun membeberkanbahwa pada tahun 1830, sistem penjajahan yang sebenar-benarnya dalam sejarah Indonesia baru akan dimulai.
Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2017) pun membeberkanbahwa pada tahun 1830, sistem penjajahan yang sebenar-benarnya dalam sejarah Indonesia baru akan dimulai.
Sebagai pungkasan, buku ini dapat menjadi rekomendasi menarik bagi para penikmat kajian Tasawuf di Jawa. Sebab, buku ini kaya akan pembahasan kasusastraan Jawa yang bernafas tasawuf.
Mulai dari karangan pujangga keraton seperti R.Ng. Ronggowarsito dengan Wirid Hidayat Jati, Suluk Suksma Lelana, Serat Saloka Jiwa dsb. Tak lupa juga Serat Wedhatama karya K.G.P.A.A Mangkunegara IV yang mengisi kepustakaan sastra di Jawa.
Judul: Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Tasawuf Mistik
Penulis: Dr. Simuh
Penerbit: Narasi
Cetakan: April, 2018
Tebal: vi + 322 halaman
ISBN: 978-979-168-472-9